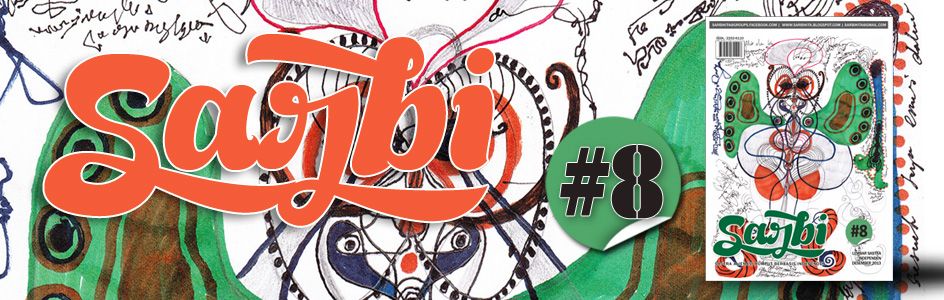Judul buku
: Anak-Anak Revolusi (Buku I)
Penulis :
Budiman Sudjatmiko
Penerbit :
Gramedia Pustaka Utama
Halaman :
xv + 473 hal, cet 1, 2013
ISBN :
978-979-22-9943-4
[Membongkar Sifat Megalomania dalam Buku Anak-Anak Revolusi]
Oleh: Ubaidilah Muchtar
Pada ulang
tahun yang ke-150 novel Max Havelaar, tahun 2010 lalu, panitia membuat tema
yang cukup mengejutkan. Tema peringatan itu: “Ini bukan roman. Ini sebuah
gugatan.” Max Havelaar ditulis Multatuli. Max Havelaar sebuah roman
kepahlawanan pembela rakyat tertindas.
Sementara
itu, Haji Budiman Sujatmiko tidak menulis novel, “Aku memang tidak cukup
nekad,” tulisnya, “untuk menulis novel yang dia maksud, tapi hanya catatan
refleksi ini yang bisa aku buat.” Maka anggap saja ini sebagai catatan atas
catatan refleksi Budiman Sudjatmiko yang tertumpah dalam Anak-Anak Revolusi
(Gramedia, 2013).
Multatuli
menulis novel Max Havelaar dalam keadaan lapar dan miskin. Pada awal 1858
Multatuli tiba di Brussel, Belgia. Tinggal di kamar loteng sebuah penginapan
yang kumuh bernama “Au Prince Belge”, di Jalan De La Fourche Nomor 52.
Di kamar
kecil itu lahir kreasinya yang kemudian menjadi termasyhur, berjudul Max
Havelaar. Dalam novel yang lebih merupakan otobiografi ini, dengan keras
Multatuli mengecam pemerintah Belanda yang membiarkan berlakunya tindakan yang
sewenang-wenang, di mana dia sendiri selaku saksi mata.
Di tempat
penginapan itu, Multatuli menderita kedinginan. Willem Frederik Hermans, dalam
bukunya Multatuli yang Penuh Teka-Teki menulis menulis, “Ia bergerak di kalangan
rendah, karena di sanalah ia menemukan manusia-manusia, dan manusia tidak
ditemukan di kalangan tinggi.”
Dengan
singkat Max Havelaar mengemukakan tiga dalil:
Pertama,
orang Jawa dihisap dan dianiaya. Kedua, pejabat yang menentang perlakuan itu
oleh pemerintah tertinggi disalahkan, demi kehormatannya ia harus minta
berhenti, dan hidup dalam kelaparan. Ketiga, negeri Belanda berkepentingan
dengan penganiayaan orang Jawa. Mereka menutup mata dan mengantongi keuntungan.
Jadi
kesimpulannya tidak bisa lain dari: sistem kolonial adalah keaiban, harus
diakhiri. Dan dilihat secara demikian maka Max Havelaar adalah suatu serangan
terhadap kolonialisme dalam bentuk roman.
Kita boleh
bertanya apakah maksud Multatuli memang demikian?
Namun
rasanya kurang pas jika terus membicarakan Max Havelaar. Baiklah, kita memulai
saja membaca Anak-Anak Revolusi.
Anak-Anak
Revolusi berisi kisah hidup kepahlawanan Budiman. Mungkin lebih tepat disebut
otobiografi politik Budiman. Membaca buku Budiman akan mengingatkan pada buku Soeharto
yang berjudul Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989). Tidak
mengherankan kalau seperti buku Soeharto, kisah heroisme Budiman akan kita
dapatkan di seluruh batang tubuh buku tersebut. Bukalah halaman berapa saja,
maka Anda akan mendapatkan kisah kepahlawan ala Rambo, Superman, Batman atau
Steven Seagal: tidak terkalahkan.
Yang
pasti, Budiman tidak menuliskan karyanya seperti kondisi ketika Multatuli
menulis Max Havelaar. Kalau Multatuli menulis dalam keadaan kelaparan dan
kedingan, Budiman sebaliknya, ia menulis dalam keadaan serba kecukupan.
Pundi-pundi yang didapatkannya dari menjadi anggota DPR cukup membuatnya
menulis dalam situasi nyaman. Capek menulis di rumah, ia dengan mudah bisa
pindah ke café kelas atas sambil menghisap cerutu dan menegak wine. Maka,
kalaupun memakai kata “refleksi” di sana, Anak-Anak Revolusi adalah “refleksi”
orang berduit. Atau Anda bisa juga menyebutnya semacam buku motivasi semacam
Laskar Pelangi atau Negeri 5 Menara—yang sejak dalam kandungan sudah ditakdirkan
menjadi hero. Yang akan memotivasi Anda bagaimana menjadi orang yang sukses. Di
sini peran Haji Budiman 11-12 dengan Mario Teguh.
Anak-Anak
Revolusi Buku 1 berkisah sejak kelahiran Budiman hingga masa ditahan.
Sebagai pembaca, saya hampir
mencampakkan buku ini. Tetapi saya terus menamatkannya. Bahkan membukanya
kembali ketika hendak menuliskan catatan ini. Dan mendapati bahwa meski di
bagian ucapan terima kasih, Budiman menyebutkan bahwa buku ini bukan tentang
diriku, tetap saja ini tentang diri Budiman. Budiman yang heroik. Budiman yang
tidak pernah kalah. Budiman yang selalu menang. Budiman yang tidak pernah
setengah-setengah. Budiman yang selalu berada dalam lindungan Tuhan di setiap
kesempatan. Budiman yang selalu mendapati keberuntungannya sendiri. Budiman
yang sempurna, Budiman yang menjadi “manusia lengkap”. Persis film hero ala
Hollywood.
Loh, kok
bisa begitu? Tentu bisa! Baik saya coba uraikan satu demi satu.
Buku ini
tentang Budiman, tidak dengan yang lain. Semua yang tertulis adalah aku. Aku, Budiman.
Aku yang penuh kepahlawanan. Aku yang heroik. Aku yang kelak diberi status
sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996. Tiga cap lantas menempeli Budiman:
buronan, subversif, dan komunis. Sejak saat itu Budiman memulai kehidupan dalam
pengejaran dan pemenjaraan.
Situasi
ini ternyata di luar perkiraanku. Setiap jam namaku muncul di radio maupun
televisi. Rezim ini menuduhku sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996. Aku
peroleh status seperti yang pernah disandang oleh Jesse James, Kusni Kasdut,
atau Carlos The Jackal. Aku disebut sebagai buronandan komunis. Ketiga cap itu,
disadari betul oleh Budiman, adalah license to kill yang akan dipakai oleh para
pengecut itu untuk membuang mayat kami ke mana saja mereka suka, seandainya
mereka mendapatkan kami. Mereka beramai-ramai mengutuk PRD. (hal 15-16)
Tentu
saja, Budiman tahu. Tidak hanya ia, tetapi PRD. Namun dalam Anak-Anak Revolusi,
PRD adalah Budiman—sederatan nama memang disebut di situ, tetapi hanya figuran;
tokoh-tokoh yang bernama tetapi tidak ada karakternya sama sekali; sang Steven
Seagal tetap saja Haji Budiman Sudjatmiko.
Tak
kusangka bahwa kekerasan massal serupa akan terjadi dua belas tahun setelah
itu, dan akulah yang menjadi salah satu figur sentralnya. (hal 200)
Lagi-lagi
aku. “Aku terpilih sebagai ketua PRD melalui voting,” tulis Budiman. Lalu masih
menurut Budiman, “Aku terpilih sebagai ketua setelah mendapat bisikan dari
seorang kawan: “Siapa pun yang tidak berani berperang,” bisiknya, “tidak layak
merayakan kemenangan.”” (hal 428)
Maka aku
merayakan kemenangan.
Aku
terpilih sebagai anggota dewan. Sebuah cita-cita yang sudah melekat di kepala
Budiman sejak masih belia, sejak SMP. Pada persimpangan kehidupan ini akhirnya
kutetapkan sebuah pilihan. Aku ingin menjadi seorang politisi di era demokrasi (hal
202). Ah, sungguh baru saya tahu! Sayang sekali jalan hidup PRD ini. Anggotanya
dikibuli oleh Budiman. Mereka tidak tahu bahwa Budiman sudah merencanakan
hidupnya sejak belia. Budiman ingin menjadi politisi. PRD hanyalah jembatan dan
kawan-kawan seperjuangannya hanyalah undakan untuk sampai pada singgasana yang
ingin digapainya. Widji Thukul, Suyat, Bima Petrus, dan Herman Hendrawan
hanyalah kepala-kepala yang diinjak Budiman agar ia bisa sampai ke atas.
Bagaimana
dengan kawan yang tak kembali? Entahlah. Mungkin tidak ambil pusing. Namun,
tidak demikian. Ada juga rasa Budiman untuk mereka yang tak kembali. Bagi
Budiman mereka yang tidak kembali itu bukan “dihilangkan” namun
”menghilang”—silakan pembaca merenungkan perbedaan makna kata itu.
Thukul
adalah seorang penyair kampung kumuh dari Solo, yang sehari-hari hidup bersama
pemulung dan tukang becak. Yang menyamakan keduanya (Thukul dan Neruda—pen)
adalah meraka hidup dan mati (dalam kasus Thukul: menghilang) bersama
konjungtur perjuangan rakyat jelata yang mereka cintai sepenuh hati. (hal 350)
Menghilang.
Sengaja saya tebalkan. Bukan dihilangkan, bukan dibunuh. Tidak seperti syarat
yang begitu menakutkan jika hendak menjadi ketua PRD atau menjadi pengurusnya,
3B: Bunuh, Buang, Bui. Ya, 3B sebagai sebuah konsekuensi yang mungkin akan
dialami oleh pimpinan PRD. “Namun syarat yang ada cukup untuk menyiutkan
nyaliku. Syarat itu kami sebut dengan 3B: Bunuh, Buang, Bui.” Tulis Budiman.
Soal 3B ini diulang sebanyak tiga kali. Budiman seolah menegaskan bahwa 3B adalah
syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Namun
mengapa mengatakan Thukul menghilang. Bukankah Thukul adalah bagian dari
pimpinan? Seperti yang ditulis Budiman sendiri: Yang bergerak membangun
“Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jakker). Organisasi yang bergerak di sektor
kebudayaan ini dideklarasikan di akhir tahun 1994. Widji Thukul, sastrawan
rakyat dari Solo, menjadi motor organisasi ini. (418-419)
Lain
Thukul lain pula Bima Petrus. Bima tentu saja sudah bersama Budiman sejak
peristiwa 27 Juli. Hari itu, menjelang sore, Budiman bersama Bima menuju kantor
NU. Dari sana mereka bergerak ke Utan Kayu. Bertemu Goenawan Mohamad, Marsilam
Simanjuntak, Bondan Gunawan, dan sejumlah aktivis LSM. [Aduhai, ternyata
teman-teman Budiman orang-orang PSI, yang pada tahun 1965 ikut mengganyang
orang-orang komunis] Menjelang tengah malam, bersama Bima Budiman pergi ke
rumah tanteku di daerah Rawasari. Budiman tentu sangat dekat dengan Bima.
Maka
ditulisnya: “Sangat menyedihkan, saat kejatuhan Soeharto tiba, Bima tak sempat
menyaksikannya.” Dua tahun kemudian, beberapa minggu sebelum Soeharto jatuh,
Bima hilang sampai sekarang. (hal 13)
Budiman
tidak pernah tidak beruntung. Budiman selalu beruntung. Keberuntungan selalu
menyertai Budiman. Budiman lolos dari kecemasan akan kematian yang mengerikan.
Budiman juga beruntung sebab penjaga sel tidak mengambil obat maag dan
pulpennya. Kecerobohan Orde Baru juga merupakan keberuntungan bagi Budiman. Apa
itu? Dibiarkannya menyimpan banyak buku di ruang sel.
“Oh…
rupanya kantor BIA”, pikirku.
Saat itu
ketakutan atas kematian sudah mulai memudar. Kupikir sudah lebih aman sekarang.
Kami dibawa ke kantor mereka dan para pemimpin mereka telah menampakkan
wajahnya. Bila kami akan segera dibunuh, pasti tidak akan dibawa ke kantor dan
bertemu dengan pimpinan mereka. Ada kelegaan yang mulai menjalar. (hal 212)
Aku cukup
beruntung karena penjagaku tidak mengambil obat maag dan pulpen yang ada di
sakuku. Keduanya adalah benda berharga yang beguna untuk menjaga kewarasanku.
(hal 220)
Salah satu
“kecerobohan” Orde Baru saat mereka memvonisku 13 tahun penjara pada 1997
adalah mereka membiarkanku menyimpan banyak buku di ruang sel kami. (hal 88)
Juga
betapa beruntungnya Budiman selamat dari kejaran tentara di Blangguan,
Sumberwaru, Banyuputih, Situbondo. Beruntung dapat berkumpul dengan
kawan-kawan. Dan beruntung dilindungi oleh penduduk desa. Lalu apa yang
dilakukan Budiman dengan begitu banyak keberuntungan dalam hidupnya ini?
Mungkin tidak melakukan apa-apa. Bagaimana bisa yang begitu banyak
keberuntungan menjadi seorang politisi? Apa prestasinya? Apakah menjadi bagian
dari peristiwa 27 Juli? Pernah di penjara? Menjadi ketua PRD? Mengapa bertanya demikian?
Sebab banyak yang dilunasinya setelah Budiman menjadi anggota dewan.
Menyelesaikan kuliah yang terbengkalai—hidup di apartemen milik Haryono Isman
[mantan politisi Golkar dan sekarang di Partai Demokrat, yang nyaman di Inggris
sana]. Juga membayar janji kepada petani.
Aku cukup
beruntung janji tersebut berhasil kupenuhi 13 tahun kemudian. (hal 344)
Sebuah
janji yang ternyata baru berhasil kupenuhi delapan belas tahun kemudian saat
aku sudah menjadi anggota DPR. (hal 346)
Baik kita
kembali ke pokok.
Suatu hari
di bulan Juli tahun 1996, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI) dengan wajah serius, Munir, memintaku dan Kurniawan bertemu di kantor
YLBHI. Keesokan harinya aku bersama Petrus dan Kurniawan mendatanginya. Pria
kelahiran Malang ini menyambut kami di halaman kantor YLBHI. Dia lalu mengajak
kami bertiga ke salah satu ruangan di dalam kantor. Sambil berbisik dia
berkata:
“Bud, aku
punya informasi rahasia.” (hal 2)
Budiman
menjadikan peristiwa 27 Juli 1996 sebagai pembuka bukunya. Sebagai tema
utamanya, selain tentu jejak kehidupannya. Membaca buku Anak-Anak Revolusi
seakan hanya berisi kisah heroisme dan teror Orba dalam situasi interogasi
pasca peristiwa 27 Juli. Sebuah kejadian yang luar biasa diingatnya. Bagaimana
bisa begitu detail proses interogasi itu? Apakah ia mendapatkan transkripnya?
Mengingatnya di kepala? Atau merekamnya? Peristiwa 27 Juli 1996 serupa bagian
yang sengaja dicabut dan dipisahkan dari bagian buku ini. Terletak di akhir
bagian “Sebuah Manifesto Perjuangan”.
Akhirnya
pada tanggal 27 Juli 1996, benturan itu terjadi. Ia memercikan bunga api yang
kemudian membakar ilalang politik negeriku yang sudah meranggas kering …… (hal
448)
Seolah
ingin menegaskan sebuah pepatah: karya seorang penulis tidak akan jauh dari apa
yang dibacanya—dan ingin menunjukkan ia kutu buku dan melek budaya—Budiman
memasukkan banyak buku yang dibacanya dalam Anak-Anak Revolusi. Dalam catatan
saya setidaknya terdapat 50 buku, 15 film, dan 17 lagu. Deretan buku dan film
ini seakan ingin menegaskan sekali lagi pernyataan Budiman, bahwa, “ Nonton
film dan membaca adalah dua hobiku sejak kecil.”
Anak-Anak
Revolusi menyimpan banyak kalimat-kalimat yang layak dicatat. Juga
beberapa ungkapan dari penulis di
pembuka setiap bagian. Namun tentu tidak lepas dari kekurangan. Salah satunya.
Kapan peristiwa tabrakan motor bersama paman itu terjadi?
Catatan
lain, Anak-Anak Revolusi tersandung-sandung di sejumlah urusan detail. Segala
benda dan tindakan harus dijelaskan. Tidak mengenal metafora dan implikasi. Di
setiap rumah ada tulisan “Ini rumah, lho!”. Semua yang ingin dicapai
disampaikan oleh Budiman. Ia seperti takut jangan-jangan pembaca tidak tahu
tujuan membaca bukunya. Maka segala hal diterangkan dalam cara yang lugu dan
dalam rumusan yang membuat pembaca tidak menjadi lebih paham tentang apa yang
dirumuskan. Setiap bagian yang terdapat di Anak-Anak Revolusi dijelaskan. Maka
jangan heran kelak ada yang berseloroh. “Ini serupa diktat, diktat pergerakan.”
Budiman seolah tidak percaya bahwa setiap orang akan menemukan pemahaman
sendiri berdasarkan pengalaman masing-masing, yang tentu saja berbeda satu
dengan lainnya. Inilah buku yang ceriwis.
Seolah
Haji Budiman menempatkan diri sebagai pengkhotbah ayat-ayat suci kepada
segerombolan domba yang dungu. Ya,
memang Haji Budiman memang sedang berkhotbah tentang kepahlawanannya: inilah
aku, maka pilihlah kembali aku dalam Pemilu 2014, biar aku bisa melanjutkan
kepahlawanku membebaskan orang miskin dari ketertindasan.
Selain
itu, masih terdapat kesalahan penulisan di halaman 410, 413, 416, 423, 428,
441, 464.
Satu lagi,
apakah sebuah dosa tidak menampilkan secara utuh puisi Widji Thukul? Apakah
puisi “Peringatan” tidak lebih layak dari lagu “Ambilkan Bulan, Bu”, karya A.T.
Mahmud? Ah, itu kan prasangka saja! Ya, saya percaya Multatuli pernah berkata,
“Anggota Dewan,” katanya, “tidak layak untuk diikuti dan disalahpahami.”
Budiman
menulis bukunya dalam kondisi kenyang dan kaya. Juga tinggal di kota besar.
“Kota-kota besar,” katanya, “hanyalah muara tempat berkumpulnya sampah dan
bangkai yang diseret banjir bandang kemiskinan dan ketakutan yang melanda
desa-desa.” Lalu mengapa Budiman meninggalkan desa dan memilih kota?
Meninggalkan petani yang katanya dibelanya. Semoga Budiman tidak termasuk ke
dalam golongan sampah dan bangkai. (hal 187)
Dan apakah
Budiman takut jika pembacanya kelak lebih banyak yang hafal puisi Thukul
daripada lagunya A.T. Mahmud?
Sebagai
penutup saya sampaikan puisi “Peringatan” karya Widji Thukul.
Jika
rakyat pergi
Ketika
penguasa berpidato
Kita harus
hati-hati
Barangkali
mereka putus asa
Kalau
rakyat bersembunyi
Dan
berbisik-bisik
Ketika
membicarakan masalahnya sendiri
Penguasa
harus waspada dan belajar mendengar
Bila
rakyat berani mengeluh
Itu
artinya sudah gawat
Dan bila
omongan penguasa
Tidak
boleh dibantah
Kebenaran
pasti terancam
Apabila
usul ditolak tanpa ditimbang
Suara
dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
Dituduh
subversif dan mengganggu keamanan
Maka hanya
ada satu kata: LAWAN!
(Solo,
1986)
Saya tutup
catatan ini dengan ungkapan dari Multatuli. “Sikap setengah hati tidak akan
menghasilkan apa-apa. Setengah baik berarti tidak baik; setengah benar berarti
tidak benar.”***
Ubaidilah
Muchtar, Guru SMPN Satu Atap 3 Sobang, Pemandu reading group Max Havelaar di
Taman Baca Multatuli, Lebak, Banten.
______________
Redaktur
SARBI: Dody Kristianto