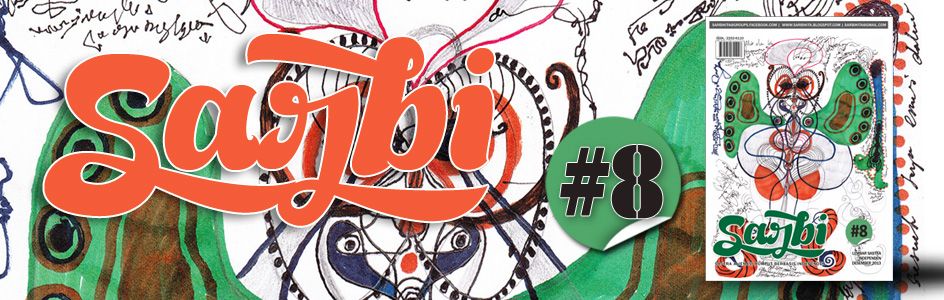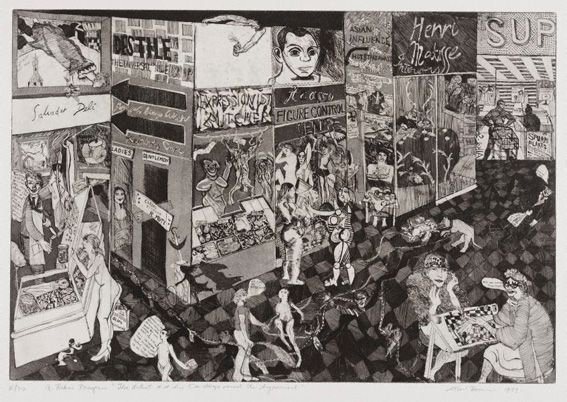Man Reading karya Georges Lemmen
Oleh: Fandy Hutari
Di kamar kontrakan berukuran empat kali lima meter,
mata saya masih tenggelam di dalam layar netbook yang terpenuhi oleh
huruf-huruf. Sebotol minuman soda tumpah membasahi hamparan buku yang menyesaki
kamar sempit ini. Saya masih tercenung, mengingat saat-saat perpisahan kita,
lebih dari dua bulan yang lalu. Kepala saya yang botak menjadi berkilap karena
terpantul sinar bola lampu lima puluh watt yang menerangi setiap sudut kamar
ini. Pantulannya membalikkan tabir memori masa lalu yang teramat pedih. Seekor
kuda menyeringai dari bawah kasur kapuk yang menghampar tepat di belakang saya.
Suara kayu yang dibenturkan di tiang listrik tepat di depan kamar kontrakan
saya nyaring berbunyi tiga kali.
Ting! Ting! Tiiiinggg!
Suara-suara itu membawa saya keingatan usang yang sebenarnya sudah saya
bakar menjadi arang. Cerita soal buku dan sebatang cokelat.
1
Kita terbiasa jalan-jalan bersama. Menyusuri
gunung-gunung yang menjulang ke langit, menelusuri rimbunan pepohonan yang
akarnya menyentuh bumi, menyeberangi sungai-sungai yang mengelok dan berarus
deras, hingga terbang menuju angkasa yang luasnya segenggaman Tuhan. Kita terbiasa
jalan-jalan bersama, namun itu semua cuma dalam pikiran kita berdua.
Kamu terbangun dan menyingkirkan lengan saya yang mendekapmu semalaman
ini. Matamu yang belum dilapisi lensa membuat saya terpacu membayangi lagi
malam tadi.
Mana bukumu, katamu mengagetkan lamunan jorok saya. Saya
seperti sedang tersengat pantat lebah di hidung.
Belum. Kata penerbitnya akan terbit akhir bulan ini, jawab saya. Saya juga
bangun. Lalu duduk di depan cermin. Memakai lipstik dan parfumnya.
2
Matahari menyeruak menerobos fentilasi yang
terdapat di sudut kamar mandi satu-satunya di kontrakan ini. Saya sedang
mencuci. Mencuci pakaian. Nah, inilah hobi saya selain menulis di kamar. Dari
lubang jamban, terdengar suara gemercik air. Seekor kobra keluar dari sana.
Membawa aroma bau kotoran yang tak enak jika engkau menciumnya. Busa-busa dalam
ember membentuk gelembung yang terbang ke udara. Pecah, dan menghadirkan memori
yang membalikkan ingatan saya ke cerita buku dan sebatang cokelat.
3
Ada seekor kupu-kupu yang keluar dari kelopak
matamu, menembus lensa kacamatamu, dan menusuk bola mata saya. Setelah itu,
kupu-kupu berubah menjadi cairan yang menembus urat-urat darah saya. Menuju
jantung dan menulari hati saya yang sudah lama membeku bagaikan es.
Itu mungkin yang dimaksud orang-orang dengan cinta. Padahal, saya tak
pernah menanggapi perasaan itu. Namun, karena kita sering berjalan-jalan dan
sering bersama, perasaan itu timbul secara otomatis.
Sore itu, kamu mengajak saya ke dataran tinggi tengah kota Bandung. Kita
berdua, bersama-sama menyaksikan pemandangan gedung-gedung yang seperti
tumpukan balok kayu. Di mata saya cuma ada kamu. Orang-orang yang hilir-mudik
saya anggap kapas-kapas yang melayang-layang. Mulut saya yang sejak tadi
terkunci, tiba-tiba mengucapkan sesuatu. sesuatu yang selama ini saya pendam
dalam-dalam. Saya sayang kamu, ucap
saya.
Maaf, aku tidak bisa menerimamu. Ada lelaki lain dalam hidupku, katamu. Air matamu jatuh. Air itu, menguap di
udara saat hampir menyentuh tanah yang sama-sama kita pijak. Saya cium kening
kamu. Mengusap air matamu. Memelukmu erat-erat. Enggan saya berpisah darimu
setelah ini. Tiba-tiba, kaus yang
kamu pakai itu bertukar dengan kaus saya. Saya sekarang memakai pakaianmu.
Aroma parfum tubuhmu yang khas dapat saya endus dengan tegas. Mata kapas-kapas
tadi memerhatikan saya dengan tatapan aneh yang menelanjangi seluruh tubuh
saya.
4
Menjemur pakaian sendiri ibarat mengeringkan tubuh
saya sendiri. Menyinarinya dengan sengatan matahari yang panas dan terik. Saya
suka menjemur pakaian. Menjepit kaus, jaket, jeans, kemeja, dan celana dalam
saya supaya angin yang menggoda mereka tak melepaskannya dari tambang yang
membentang.
Seekor laba-laba membuat jaring berantakan di atap rumah tetangga.
Laba-laba itu menggelayut di benang yang ia buat sendiri. Saya seperti
melihatnya menggantung pakaiannya sendiri. Angin sepoi-sepoi membelai kepala
botak saya. Membuat kesejukan yang memacu adrenalin emosi. Irama musik dangdut
mengalun dari kamar tetangga. Suara Bang Haji Rhoma Irama yang menyanyikan lagu
“Begadang.” Begadang
jangan begadang…Kalau tiada artinya…Begadang boleh sajaaaa…Kalau ada perlunya,
saya spontan menyanyikan reff-nya.
Nah, tiba-tiba saya ingat lagi masa-masa itu. Cerita soal buku dan
sebatang cokelat.
5
Valentine. Saya sendiri tak tahu mengapa anak-anak
muda merayakan hari yang jatuh pada tanggal empat belas Februari setiap tahun
ini. Padahal, sejarahnya Valentine identik dengan pesta seks. Nah, sekarang
pesta seks dirayakan setiap tahun beramai-ramai, berarti hehehe...
Lelaki lain yang mengungkung hatimu memberikan sebatang cokelat kepadamu. Aku dapat cokelat dari Rizal semalam dan
mengucapkan selamat hari Valentine, katamu kepada saya saat kita berdua berada
di lantai dua, tempat menjemur pakaian di kontrakan saya. Duduk di bawah cahaya
bulan yang bulat penuh. Saya
terdiam. Kemarin
tukang pos ke sini. Dia memberikan sepuluh eksemplar buku saya. Sebelumnya,
penerbitnya menelepon saya, dan mengatakan buku saya sudah terbit, ucap
saya.
Serius? Mana? Aku mau lihat, sahutmu.
Saya masuk ke kamar, setelah menuruni tiga belas anak tangga yang
terbuat dari kayu yang telah lapuk karena dilahap rayap. Mengambil buku saya
yang berada di meja kecil, samping netbook yang masih menyala.
Ini, kata saya setelah memberikan buku itu kepadanya. Wah,
bagus bukumu, pujimu kemudian.
Saya berikan buku itu untuk kamu. Buku lebih abadi daripada sebatang
cokelat. Lihat di lembar pertama. Ada namamu di sana. Dan, namamu akan terus
tercatat di buku saya, selama-lamanya, bahkan saat kita berdua mati dan
dikerubungi oleh belatung-belatung tanah, Margianna, ujar saya menatap
dalam-dalam kedua bola matanya.
Kamu tertunduk. Mungkin malu. Mungkin pula jijik. Tapi, saya tidak
peduli apa yang kamu rasakan setelah ini. Bulan hilang ditelan awan kelabu.
Rintik gerimis ambles dari langit, membasahi kita berdua. Kacamatamu saya
pakai. Dan, kamu berkepala botak.
6
Foto kamu saya gilas asbak yang sudah penuh puntung
rokok. Saya benci kamu yang sudah memilih lelaki itu menjadi tunanganmu. Bara
rokok yang terjatuh membakar pinggiran gambar fotomu. Saya masih terus
mengembuskan asap. Menikmati nikotin berbatang-batang sambil membayangi kamu di
sini lagi.
Kata orang-orang, saya ini penulis ecek-ecek. Penulis yang masih kerdil
karena tidak populer. Kamu juga menganggap saya demikian.
Lalu, buat apa populer bagi seorang penulis?! tanya saya kepadamu di
ujung gang menuju kontrakan saya malam itu. Saya mencintai buku, sama seperti
saya mencintai kamu! tegas saya kepadamu.
Kamu cuma terdiam. Kamu lebih memilih seorang dokter daripada seorang
penulis rupanya. Suara anjing menggonggong. Kemudian malam menjadi sepi. Senyi.
Senyap. Lampu yang menggelantung di badan tiang listrik di atas kita
seakan-akan menutup matanya. Ia redup, lalu mati.
Mata saya mengedip, menyapu asap rokok yang menusuk penglihatan. Rokok
pun saya lumat di asbak yang, seperti saya katakan tadi, sudah sesak akan
puntung rokok. Saya melihat buku saya sendiri, bertumpuk di meja kecil samping
netbook. Buku itu sekarang terlihat sangat menjijikan bagi saya karena ada nama
kamu. Lebih baik saya membaca koran kemarin sore. Tiba-tiba telepon seluler
saya berdering. Rupanya si Anto yang menginginkan saya berdiskusi soal buku
saya di perpustakaan miliknya di Jatinangor. Saya membanting telepon di
genggaman ke arah buku saya sendiri. Brak! Hancur.
Jati! Jati! Jati! teriak Anto yang terdengar pelan setelah tutup baterenya
terlepas dari badan telepon itu. Lalu mati.
Alunan lagu “Will You Still be There” Daniel Sahuleka mengalun
menyayat-nyayat pendengaran saya. Menggarami hati saya yang tergores luka.
Jarum jam dinding yang terpaku miring di atas jendela berdetak.
Tak…Tak..Tak…Pukul dua dini hari.
Apakah saya seorang pria yang amatiran mendekati perempuan? Kata hati
saya seketika, saat meremas kaleng bir berwarna putih. Perut saya masih kosong.
Dari siang belum ada nasi yang merasuk ke perut ini. Cuma berkaleng-kaleng bir
dan isapan rokok. Saya ingin muntah. Rasanya ada seekor naga yang ingin keluar
dari mulut saya. Ah,
cinta sejati saya sekarang cuma sepi dan buku. Saya mencintai buku lebih
daripada saya mencintai kamu. Saya tutup cerita soal buku dan sebatang cokelat
sampai di sini.
7
Tiga ketukan mendarat di pintu kamar saya. Membuat
saya terpaksa menarik seluruh mimpi menuju ke alam nyata. Masih pukul lima
subuh. Saya bergegas bangkit dari kasur, menuju pintu. Mungkin si Amir yang
ingin membayar hutangnya. Kebetulan, uang saya juga sudah menguap beberapa hari
belakangan ini. Gagang pintu saya tekan, dan pintu saya buka. Ternyata, yang
datang adalah perempuan yang membawa buku saya dan sebatang cokelat. Dia
memakai kaus yang tadi saya kenakan sewaktu tidur. Aih…
Bandung, dini hari, 21 Juni 2011
Fandy
Hutari, lahir di Jakarta 17 Agustus 1984,
penulis, editor buku, dan jurnalis lepas. Bukunya yang sudah terbit Sandiwara
dan Perang; Politisasi Terhadap Aktivitas Sandiwara Modern Masa Jepang (Ombak,
2009), Ingatan Dodol (IMU, 2010), Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal
(INSISTPress, 2011). E-book berjudul Menulis di Media Massa, Why Not. Kumpulan
cerpennya yang akan terbit berjudul Manusia dalam Gelas Plastik. Tinggal di
Bandung.
Redaktur
SARBI: @Dody Kristianto