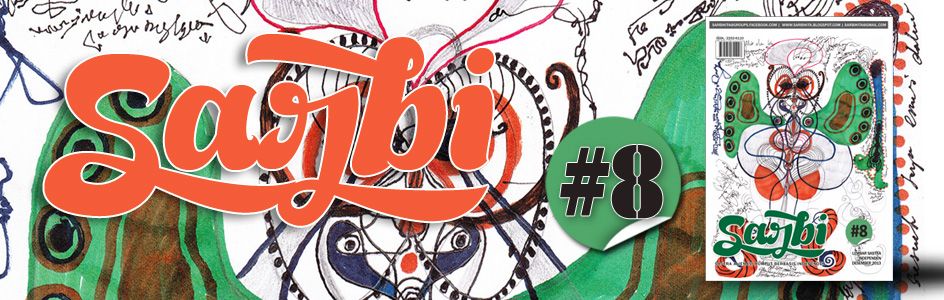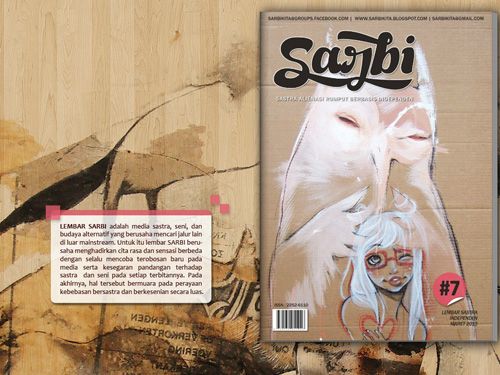"Where is my mind?" artwork by bernardumaine
Oleh Umar Fauzi
Membaca sejarah sastra (baca, perpuisian) Indonesia –pun mungkin kesusastraan
dunia– dengan cara sederhana adalah membaca
pengotakan zaman, sebagai khazanah yang coba dimitoskan ke dalam
angkatan-angkatan atau periodeisasi kesusastraan. Dari bentukan
angkatan/periode itulah, kritikus –secara sadar maupun terpaksakan– menemukan
benang merah hingga layaklah disebut sebagai sebuah angkatan bla-bla-bla
kesuasatraan Indonesia. Ini menjadi makfum, sebagaimana diungkapkan oleh Dami N
Toda, tentang “benang merah” bahwa
hadirnya kesamaan pencerapan diakibatkan “roh waktu” alamiah yang biasanya
muncul sebagai trend mode karena lingkungan kode, simbol
budaya, konversi dan konsumsi budaya yang sama. Secara praktis pun usaha ini
memunyai kepentingan besar bagi perbendaharaan museum sastra Indonesia di masa
mendatang, terutama bagi para pemerhatinya.
Menarik dari apa yang diungkapkan oleh
Dami N Toda tersebut, adalah juga pembagian atau pemetaan sastra menurut
“daerah estetika” yang dapat ditelaah melalui keberadaan/ tempat tinggal
sastrawan. Jadi tidak hanya pembagian dalam arti kurun waktu, sastra Indonesia,
telah menggoda para kritikusnya untuk melihat sengkarut proses kreatif dengan
keberadaan sang penyair. Terjadi kemudian, wilayah geografis itu, tidak hanya
dibaca sebagai usaha pencapaian estetik individu, namun penemuan corak-corak
keterwakilan yang dibaca secara komunal sebagai ciri karya sastra daerah
bla-bla-bla.
Usaha untuk ini sudah cukup
banyak, misalnya yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta, bertajuk “Cakrawala
Sastra Indonesia” tahun 2004 membuat antologi sastrawan masing-masing provinsi,
diterbitkan oleh penerbit Logung dan Akar Indonesia. Antologi Jawa Timur dalam
program tersebut adalah Birahi Hujan,
memuat puisi Mardi Luhung, W. Haryanto, Indra Tjahyadi, Tjahjono Widijanto, dan
Tjahjono Widarmanto dengan kurator Zawawi Imron. Majalah Horison,
misalanya juga pernah menerbitkan edisi daerah. Antologi kota misalnya dapat
dibaca pada antologi Lima Pusaran, Bunga Rampai Puisi
Festival Seni Surabaya 2007, penyunting Nirwan Dewanto, memuat puisi-puisi
Zen Hae (Jakarta) Iswadi Pratama (Lampung), Gunawan Maryanto (Jogja), S. Yoga
(Surabaya), dan Sindu Putra (Bali).
Dari serangkaian antologi
“wakil” wilayah geografis itulah, mencuat dan menjadi menarik adalah perhatian
para kritikus terhadap puisi-puisi Jawa Timur (dibaca juga, Surabaya), yang
katanya, keluar “terlalu jauh” dari maenstream perpuisian Indonesia. Inilah puisi
gelap.
Resepsi menarik itu dapat
dibaca seperti pendapat berikut. Puisi-puisi gelap sebagai akibat salah baca
terhadap surealisme yang coba diusung sebagai “ideologi” kata Binhad Nurrohmad
(dalam Sastra
Perkelaminan, Pustaka Pujangga 2008);
kecenderungan apokaliptik, ceramah Abdul Hadi pada waktu “Cakrawala Sastra
Indonesia” dan kata pengantar Arif B.
Prasetyo untuk Antologi Lima Penyair
Jatim, Rumah Pasir, Festival Seni Surabaya 2008; Nirwan Dewanto mengatakan
“puisi (Surabaya) yang menjelma keajaiban atau keganjilan dengan kocokan maut
kata-kata.”
Memang yang mengemuka dalam peta penyair Jawa Timur, kebanyakan
dari mereka adalah penyair-penyair yang matang berproses di Surabaya, utamanya
dari kampus, seperti W. Haryanto, Mashuri, Indra Tjahjadi, S. Yoga, Tjahjono
Widarmanto. Terlepas dari Surabaya yang menjadi inspirasi kelangsungan hidup
mereka, Surabaya adalah delta pertemuan menarik, sebelum akhirnya para penyair
itu kembali ke kampung halaman, sehingga puisi gelap tidak hanya dibaca sebagai
Surabaya, akan tetapi ia adalah milik Jawa Timur.
Puisi gelap itu tak hanya
dibaca sebagai capaian estetika individu, ia juga dibaca sebagai Surabaya,
bahkan juga dibaca sebagai Jawa Timur. Karena itulah ia pun tak lagi dibaca
sebagai pencapaian estetika individu, akan tetapi berubah menjadi “ideologi”
komunal.
Perilaku ini ditemui pada
“proklamasi” antologi Manifesto Surrealis oleh W. Haryanto, Mashuri, Indra
Tjahjadi, dan Mohamad Aris. Jejak itu juga terasa dalam antologi tunggal
mereka. Garda inilah sebenarnya yang cukup mengejutkan publik sastra Indonesia.
Dengan membawa semangat Andre Breton, pencetus Surealisme, mereka mengira telah
sampai pada taraf surealisme yang dimaksud, yang terjadi adalah puisi-puisi
mereka jatuh pada “kegelapan.” Di sinilah rumusan puisi surrealis dan puisi
gelap perlu dikonkretkan kembali.
Secara historis, Surabaya
–sebelum puisi madzab “surealis” ini ada– telah ada prosa surealis yang
dikatakan juga “anti novel” diciptakan oleh pengarang Iwan Simatupang dan Budi
Darma. Kedua nama inilah dikatakan sebagai pembaharu prosa Indonesia juga
sebagai pelopor prosa periode ’70an. Kehadiran dua pengarang penting ini,
setidaknya dapat dilihat dari banyaknya resepsi apresiatif terhadap karya-karya
mereka. Meskipun dikatakan ganjil dan menyimpang dari “struktur” lazim prosa,
justru estetika inilah yang dibaca sebagai kenikmatan prosa oleh pembacanya.
Bahkan novel eksistensialisme ini juga dapat dikupas dengan baik oleh pelajar
SLA, Julia Surjakusuma, pemenang penulisan esai DK Jakarta1973.
Sejalan dengan suksesnya
surealisme dalam prosa, usaha terbalik terdapat dalam khazanah puisi “kredo”
surealis Surabaya. Hal ini maklum, karena puisi memiliki struktur berbeda
dengan prosa. Menarik untuk melihat bagaimana tidak mudahnya, surealisme puisi
diterima oleh khalayak, adalah kata-kata terakhir Hasif Amini (dalam kolom
“Tilas”, Kompas, 5 Maret 2006 dengan judul
“Surealisme”) sebagai sebuah cita-cita yang
mulia, tapi alangkah sulitnya. Tapi apa salahnya… Pun apa yang dikatakan oleh S. Yoga (SINDO, 1 Juli
2007) “puisi surealis yang baik tentu saja tetap membayangkan sesuatu yang
nyata dalam ketidaknyataan. Kualitas ini harus dicapai jika tidak ingin disebut
sebagai puisi gelap.”
Polemik “puisi gelap”
Surabaya, pun secara nasional, seperti pernah dialamatkan pada puisi-puisi
Afrizal Malna tidak hanya menyangkut pola ekspresi simbolik yang terlampau
subjektif sehingga menyulitkan pembaca, akan tetapi –dalam konteks perpuisian
Surabaya– lebih kepada pilihan tema yang terakumulasikan dari diksi yang
tersebar. Jika kita membaca secara bersamaan puisi-puisi Afrizal Malna, Indra
Tjahjadi, dan Mardi Luhung misalnya, tentu persoalan puisi gelap tidak lagi
dalam konteks kesulitan dipahaminya sebuah puisi, melainkan pada jalinan
peristiwa dalam puisi tersebut juga tema yang diangkat.
Afrizal Malna sebagai
“anak”dari modernitas yang sedang berlangsung, memungut remah-remah diksinya
dari apa yang ia lihat sebagai representasi teknologi, benda-benda, dan
kegelisahan-kegelisahan di dalamnya, dalam Kalung Dari Teman, (Grasindo,1999). Atau “anak”
pesisiran, macam Mardi Luhung yang bebal dan tanpa andeng-andeng itu, dalam Ciuman Bibirmu yang
Kelabu, (Akar Indonesia,
2007). Menikmati imaji-imaji kedua jenis puisi itu, tentu akan berbeda ketika
kita menikmati sarkasme maut-nya Indra Tjahjadi, sebuah kumpulan puisi dalam Ekspedisi Waktu (2004) yang remah diksi-diksinya
tak “memijak” bumi, melainkan mengawang dan berasal dari dunia antah berantah,
mungkin lebih mirip film hantu Indonesia, ketika kita menikmatinya, pun
menikmati puisi-puisi aurat-nya Mashuri, atau kesangaran W. Haryanto.
Angkatan Baru Penyair Surabaya
Estetika gelap itu mungkin
akan atau sudah berlalu, dirasakan atau tidak, beberapa penyairnya mulai
sedikit “jenuh” dan membelot meski tidak secara terang-terangan dan malu-malu
pada pola pengungkapan baru, tengoklah misalnya puisi Mashuri, setelah Pengantin Lumpur –setidaknya yang terbit di media-media
nasional dan lokal beberapa tahun belakang– seperti dua puisinya yang termuat
antologi Pena Kencana 2008, misalnya.
Meskipun begitu masih ada studi cukup
menarik dan kontras, pabila menikmati antologi bersama lima penyair Jawa Timur
dalam Rumah Pasir,
Festival Seni Surabaya 2008. Dalam puisi itu kita melihat tiga penyair “lawas”:
Indra Tjahjadi, Mashuri, dan Denny Tri Ariyanti, serta dua penyair “baru”: A.
Muttaqin dan F. Aziz Manna. “Lawas” karena mereka masih menampilkan kegarangan
dalam kegelapan puisi-puisi
mereka. Dan “baru” karena dua penyair tersebut terakhir, adalah penyair yang
datang dengan segala respon lahir-batin terhadap kesuraman puisi-puisi
pendahulunya.
Puisi-puisi Festival Seni
Surabaya 2008 yang bertajuk Tribute to Surabaya itu, apa boleh buat, sebenarnya lebih
pantas disebut “Lima Penyair Surabaya (kota)”, bukan Jawa Timur. Ini karena
kelima penyair tersebut ternyata adalah penyair yang pernah menikmati delta
pendidikan sastra di Surabaya. Arif B. Prasetyo selaku kurator ternyata masih
diganduli kenyataan bahwa Surabaya adalah penghasil puisi apokalipstik, maka
yang termaktub dan pantas mewakili Tribute to Surabaya adalah sajak-sajak seperti yang
“lawas”. Seolah-olah Surabaya dengan dinamika sosialnya memanglah “segelap”
puisi-puisi itu, padahal Tribute to Surabaya akan lebih dinamis seandainya Arif
memahami usaha “penghijauan” di Surabaya. Setidaknya jika ini terjadi akan
lebih layak menyandang “ lima penyair Jawa Timur”, seperti halnya Pelayaran Bunga,
antologi mutakhir penyair Jawa Timur, pilihan Festival Cak Durasim 2007.
Terlepas dari kondisi keterbatasan itu, antologi Rumah Pasir akan dibaca sebagai tonggak peralihan
puisi Surabaya, yakni dari gelap menjadi terang.
Adalah A. Muttaqin, penyair
fenomenal Jawa Timur saat ini, kalau mau dikatakan sebagai pelopornya.
Kecendrungan itu setidaknya dibuktikan oleh diterimanya puisi-puisi Muttaqin
oleh masyarakat sastra Indonesia. Kemunculan penyair ini, telah mengejutkan
publik sastra Jawa Timur. Sebelumnya, Muttaqin tidak pernah ada dalam peta
penyair muda Jatim. Lihatlah misalnya tulisan S. Yoga yang menyebut nama-nama
penyair muda Jatim dalam esainya di SINDO 1 Juli 2007, tidak ada nama Muttaqin
di sana. Penyair lulusan Sastra Indonesia Unesa ini, seolah tanpa permisi
kepada pendahulu Jawa Timur, tiba-tiba langsung melejit di koran nasional.
Muttaqin telah sampai pada pencapain estetik. Membaca Muttaqin
dengan segala usahanya menarasikan flora dan fauna, seperti menikmati usaha
“penghijauan” yang sering dikampanyekan Surabaya. Ia tidak menulis
jelaga-jelaga Surabaya sebagiamana penyair pendahulunya. Puisi-puisinya pun tak
perlu dikait-kaitkan dengan falsafah Jawa Timur dalam artian psikologis maupun
sosiologis. Justru Muttaqin dengan demikian, telah melepaskan diri dari
tema-tema umum yang selama ini digarap oleh pendahulunya, semacam puisi-puisi
gelap.
Sajak-sajaknya mendamaikan
diksi dengan rima, sehingga simbolisme yang naratif bertemu dengan visualisasi
logis. Inilah mungkin yang membuat sajaknya terang benderang. minimal, pembaca
dapat terbuai oleh ketukan ritmis sajak-sajaknya, seperti orang Belanda yang
terbuai menikmati gending Jawa. Lihatlah salah satu petikan sajak ini:
Di gelap ombak, mungkin di
taman gagak, kuraba-
raba keharuman yang menanjak.
Sepasang daging
membengkak dan segala arwah
merebak
(Lukisan Kamboja)
Begitulah Muttaqin mengeksplorasi diksi dengan rima sebagai “diri”
kepenyairannya. Bunyi-bunyi puisinya melantur secara alamiah. Muttaqin cukup
jeli menangkap objek dan menyusunnya dalam kerangka estetika bahasa. Kita dapat
merasakan bagaimana konsonan /k/ menjadi ritmis yang berpadu dengan diksi yang
sekerabat seperti /ombak/
dan /gagak/
yang mempunyai asosiasi kegelapan. Begitupun dengan frasa /keharuman menanjak/,
/sepasang daging membengkak/
dan /arwah merebak/.
Puisi ini adalah narasi tentang Kamboja. Kamboja menjadi simbol imajinya pun
untuk menjelaskan tema kematian. Lukisan Kamboja dapat ditafsirkan –selain berbagai
kemungkinan tafsir– sebagai peristiwa membusuknya sebuah mayat: dilalui oleh
penanda kematian yang secara umum dimetaforkan dengan gagak, lalu mayat itu
membusuk –di sini Muttaqin menggunakan diksi ‘keharuman’ sehingga tampak
ironis, namun inilah ledakan diksinya– lalu membengkak, hingga tak berbentuk
karena arwahnya telah merebak ke tempat semestinya.
Bandingkanlah frasa dari
metafor yang disusun dalam petikan puisi-puisi berikut, “Ingatan bunga-bunga tercekik di dalam/
kemaluanmu,” (Rumah
Duan-Daun, Indra Tjahjadi) dengan “ hanya karna menanam bunga-bunga di
kepala” (Laut Lalat, A. Muttaqin); atau “saat mayat-mayat menari
–gemulai/ menorehkan darah pada tanah peradaban” (Tarian Sebuah Musim,
Denny Tri Aryanti) dengan “Seperti mayat yang
tenang, seperti langit yang/ lenggang, jika umur adalah semut yang merambat ke/
senja berat.” (Lukisan Kamboja, A. Muttaqin); atau “aku segera beriman pada
kekosongan” (Kembali Ke Neraka, Indra Tjahjadi) dengan “Raut yang/ mengajar
aku bersujud dan mengimani Yang
Tak/ Terjemput” (Ladang Siput, A. Muttaqin).
Bait-bait puisi di atas,
telah menggambarkan bagaimana A. Muttaqin merespon geliat diksi yang penuh
dengan aroma nanah dan darah yang sering menghiasi puisi Surabaya dekade awal
2000-an. “Lukisan Kamboja” yang bertema kematian digambarkan dengan demikian tenang oleh Muttaqin dan terasa logika “alur”
dan narasinya. Ini tentu berbeda dengan tema kematian yang mendominasi
puisi-puisi Indra Tjahjadi, dkk, yang berjumpalitan selayaknya penghuni neraka.
Dari sini dapat terbaca bagaimana sesungguhnya rumusan puisi
gelap, yakni bukan persoalan kesukaran dipahaminya puisi-puisi Surabaya, lebih
dari itu adalah bangunan suasana itulah yang gelap. Secara gamblang Indra
mengakui bahwa sajakku terasing dan menemukan rumahnya
dikegelapan. Puisi-puisi semacam itu mungkin lebih tepat, disebut puisi
gotik, yang tak hanya melemparkan pembaca pada kesunyian mencekam melainkan
pada kengerian.
Dari sini pula, surealisme
yang menjadi mula segala persoalan estetik yang diangkat perlu ditegaskan.
Surealisme merupakan tafsir terhadap psikoanalisis Sigmund Freud –terutama
konsep mimpi– yang diformulasikan dalam teknik penulisan puisi oleh Andre
Brenton, disebut dengan otomatisme.
Secara sederhana teknik ini adalah usaha melukiskan objek dengan naluri bawah
sadar dan menafikan prinsip-prinsip logika (seperti teori strukturalis) dalam
proses penciptaan karya seni.
Mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Sigmund Freud bahwa mimpi
adalah jalan tol menuju alam bawah sadar, maka dalam konteks ini representasi
“mimpi” yang coba dihadirkan penyair Surabaya, lebih kepada mimpi buruk yang
membuat pagi jadi buta dan gelap, dari pada mimpi indah yang membuat pagi jadi
benderang. Jadi sebenarnya inilah letak persoalannya. Senada juga dengan apa
yang dikemukakan S. Yoga di depan.
Perbandingan menarik juga dapat kita baca pada studi
puisi-puisinya Mardi Luhung yang juga “dituduh” gelap. Jika puisi-puisi
Surabaya secara sadar menasbihkan diri sebagai surealisme –yang pada akhirnya
memang berkecendrungan gelap– maka puisi Mardi Luhung adalah karnaval –istilah
Mikhail Bakhtin– imajisme dengan benih-benih diksi yang secara sadar adalah
kondisi sosio-psikologis pesisiran Jawa Timur, Gresik. Pencapaian estetik
inilah yang harus dibaca, jika ingin memasuki centang-perenang dan
hingar-bingar puisi-puisi Mardi Luhung yang ramai di tengah “nyanyi sunyi”
dominasi perpuisian Indonesia. “Siapkan cintamu bagi
dagingku, lelaki perahuku/ lekatkan seluruhnya pada pantai dan bakau-bakauan/
yang terulur dari bahasaku” (Lelaki Perahuku) demikian kata si penyair
Mardi Luhung.
Sebenarnya hampir secara
bersamaan ketika Surabaya dibaca sebagai penghasil puisi gelap, ada seorang
penyair yang berada “di luar pagar” kecendrungan tersebut. Dia adalah S. Yoga.
Ekspresi puisi-puisi S. Yoga adalah sebuah objek yang ia narasikan dengan segala
bentuk filosofis yang mengganduli sajaknya. Ia serupa pemotret ulung, yang
dengan itu ia hendak menampilkan sisi humanis, seperti petikan sajak ini: “di atas
penderitaanmu/ memang kebahagiaan yang selalu kucari/ dengan api yang menerangi
kegelapan/ sebelum tubuh habis dilalapnya” (Lilin).
Sajak S Yoga ini menemui
turunannya pada pola pengungkapan F.
Aziz Manna. Salah seorang penyair angakatan baru penyair Surabaya. Di saat
sahabat-sahabatnya masih “mengimani” kitab Manifesto Surealis –seperti Dheny Jatmiko dan Ahmad
Faishal– F Aziz Manna, tegak berdiri dengan puisinya yang sederhana bahkan
cenderung realis, seperti sajak berikut: “ternyata, waktu hanya
hitungan/ hanya cara mengeraskan kenangan/ seperti mesin pembeku dalam lemari
es” (November). Karakter puisinya memang belum selepas dan sebebas
sajak-sajak Muttaqin. Aziz masih menerima kecenderungan “umum” perpuisian Indonesia, terutama
terasa sekali pola S. Yoga.
Terlepas dari apa yang telah
saya uraikan di atas, Surabaya kini tengah memasuki era baru dalam kancah
perpuisian Indonesia. Sebuah dinamika yang akan terus bergerak mengisi
kekosongan atau mendobrak konvensi yang sudah mengalami kejenuhan dan
kepunahan. Muttaqin dan Aziz Manna adalah generasi yang secara lembut mungkin
akan mengatakan selamat tinggal kegelapan…
*) Umar Fauzi, pengamat
sastra alumnus sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya, tinggal di Sampang
Madura
Catatan : Esai ini termuat pada harian Surabaya Post pada tahun 2009 lalu.