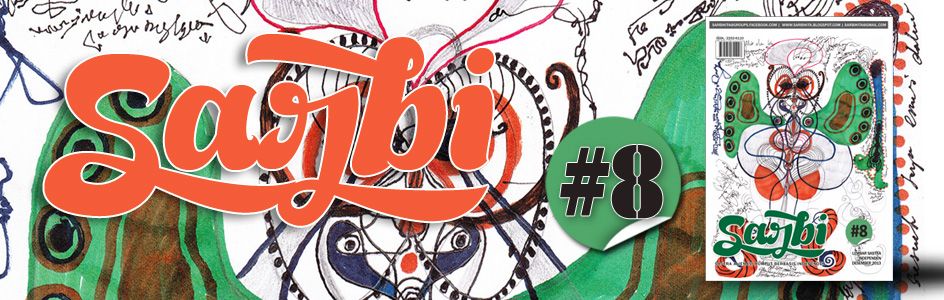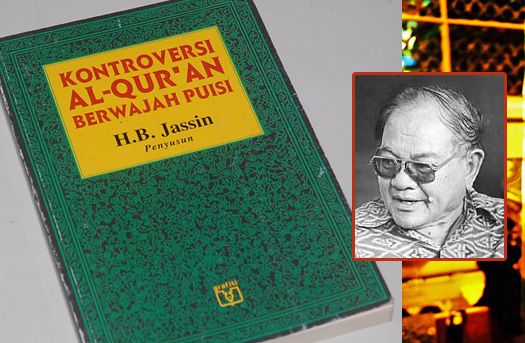Oleh Budi Setiyono
Tuhan tidak suka para penyair, kecuali yang bertakwa.
LARUT MALAM. Sesudah salat Isya, dia mulai
mengetik. Lampu 40 waat dengan kap khusus menyorot Alquran yang terbuka. Lirih-lirih terdengar
surah an-Nisaa dari qariah favoritnya, Saidah Ahmad. Dia merenung. Dipasangnya
kaset lain dan terdengarlah suaranya melantunkan surah Yassin. Disusul
terjemahannya dalam puisi bahasa Inggris, petikan dari Yusuf Ali. Juga suaranya
sendiri, seperti deklamasi. Membangun suasana seperti itu membantu pekerjaannya
menerjemahkan Alquran. Setelah menelan Bodrex, dia mengetik lagi.
H.B. Jassin sedang mengerjakan terjemahan
Alquran. “Saya melihatnya dari sudut sastra. Dan ini bukan tafsir melainkan
terjemahan - dalam bentuk puisi,” ujar Jassin dalam wawancara dengan Tempo, 29
Maret 1975.
Sosoknya tak pernah lepas dari kontroversi. Belum
juga rampung masalah cerita pendek “Langit Makin Mendung” karya Kipandjikusmin,
dimuat di majalah Sastra edisi Agustus 1968 dan dianggap menghina Tuhan, yang
membuatnya duduk di kursi pesakitan dan mendapat vonis setahun penjara dengan
masa percobaan dua tahun –salinan putusannya tak pernah dia terima– H.B. Jassin
mempersiapkan sebuah karya yang juga memantik kegalauan sejumlah ulama.
Sehari setelah pemakaman istrinya, Arsiti, pada
12 Maret 1962, Jassin menggelar tahlilan di rumahnya selama seminggu. Pada
malam kedelapan, ketika tak ada lagi orang tahlilan, Jassin membaca Alquran
sendiri. Hatinya terketuk. Keindahan bacaan dan bahasa Alquran mengilhaminya
untuk menerjemahkan Alquran dengan bahasa puisi. Dalam pengantar cetakan kedua,
Jassin juga mengaitkannya dengan latar belakang bacaan Alquran dari sang nenek
dan serangan Lekra kepada dirinya di masa Orde Lama.
“Orang sekarang berlomba-lomba menerbitkan
tafsiran yang tebal-tebal, tapi saya kira yang tak kurang pentingnya ialah
suatu terjemahan saja yang bisa dipertanggungjawabkan dari sudut keindahan
bahasa dan sudut ilmiah…,” tulis Jassin dalam suratnya kepada B. Soelarto, 17
Desember 1964, sebagaimana termuat dalam Surat-surat 1943-1983.
Dalam mengerjakan karyanya, Jassin mengumumkan
bahwa dia bermaksud membuat terjemahan baru yang bukan hanya mengungkap makna
dari teks Arabnya, namun juga mengabadikan keindahan puitisnya. “Untuk pertama
kalinya, dalam konteks Indonesia, seorang penerjemah secara terbuka memberikan
preseden bagi tercapainya padanan fungsional yang signifikan pada teks
sasaran,” tulis Peter Riddell.
Sebelum mengerjakan karyanya, Jassin mempelajari
Alquran dari berbagai terjemahan. Ada karya Mohammed Marmaduke Pickthall, The
Meaning of the Glorious Koran, yang terjemahannya, tanpa teks Alquran, disahkan
Senat Dewan Universitas Al-Azhar. Ada pula karya John Medows Rodwell (The
Koran), Arthur J. Arberry yang non-Muslim (The Koran Interpreted), Yusuf Ali
(The Holy Koran), hingga terjemahan Departemen Agama (Al-Qur’an dan
Terjemahannya). Dia juga membuka kamus, A Dictionary and Glossary of the Koran,
susunan John Penrice, yang memuat semua kata dalam Alquran.
Sepuluh tahun kemudian, setelah mempelajari
berbagai terjemahan dan mencoba mengetahui artinya kata demi kata, Jassin
merasa lega. “… alhamdulillah sekarang saya sudah sanggup menerjemahkan tidak
hanya dengan akal, tapi terutama dengan hati dan perasaan,” tulis Jassin dalam
suratnya dari Leiden kepada Kasim Mansur tanggal 24 Oktober 1972.
Jassin berada di Negeri Belanda pada 1972 karena
mendapat beasiswa dari Kementerian Pengajaran dan Ilmu Pengetahuan Belanda
untuk melakukan riset pembaruan sastra Indonesia dan mempelajari pengajaran
bahasa dan sastra di berbagai negara Eropa. Istrinya, Lily (Yuliko Willem),
ikut dengan ongkos sendiri. Di Belanda pula Jassin mencoba menyelesaikan
karyanya.
Kasim Mansur, sastrawan asal Surabaya yang juga
sahabat Jassin, adalah orang yang mendorong dan membantu Jassin dalam
menyelesaikan karya ini. Setidaknya ini terlihat dalam surat Jassin kepada
Kasim Mansur: “Terima kasih Sim, atas terjemahan Abdullah Yusuf Ali yang saya
dapat dari Kasim tiga tahun yang lalu dan atas anjuran Kasim untuk
menerjemahkan Alquran.”
Jassin tidaklah asing dengan bahasa Arab. Selama
tiga tahun dia mempelajari bahasa Arab dari A.S. Alatas, dosen Fakultas Sastra
Universitas Indonesia, dan penterjemah Al-Majdulin Musthafa Lutfi Al-Manfaluthi
–selain pelajaran ilmu-ilmu Islam dari islamolog terkenal Prof Pangeran Arjo
Hoesin Djajadiningrat. Jassin juga
menerjemahkan buku pelajaran teologi dasar al-Jawahirul Kalamiyah
sebagai latihan. “Hanya ia memang tidak secara langsung mempelajari ilmu-ilmu
seperti Ma ani-Bayan-Badi yang merupakan gerbang bagi penguasaan ilmu-ilmu alat
untuk seorang pentafsir (bukan sekadar penterjemah) Quran,” tulis Tempo, 4
Oktober 1975.
Sudah sepuluh tahun pula Jassin membaca Alquran
berurutan dari permulaan hingga habis dan kemudian diulang lagi. Jassin memulai
penerjemahan surah Al-Mu’minun karena kebetulan sedang mempelajari surah ini.
Sesudah itu, dia akan mengerjakan surah Yassin, yang populer dalam kehidupan
orang Indonesia. Kemudian surah Ar-Rahman dan Al-Waqiah karena dia anggap
secara estetis paling indah dalam seluruh Alquran karena bunyi dan iramanya.
Sesudah itu dia kembali akan menerjemahkan surah-surah sesudah Al-Mu’minun.
“Aduh Sim, makin didalami makin nikmat.
Mudah-mudahan saya berhasil mengungkapkan kembali keindahan bentuk dan
kandungannya,” tulis Jassin dalam suratnya kepada Kasim Mansur, 26 November
1972.
Sebagian terjemahannya dimuat di Panji Masyarakat
dan mendapat komentar dari kawan-kawannya, yang menganggap karya Jassin akan
jauh dari aslinya karena mendasarkan pada terjemahan bahasa Inggris atau bahasa
lainnya. Dalam surat kepada Kasin Mansur, 9 Desember 1972, Jassin membantah
anggapan itu.
“Mengenai komentar kawan-kawan, saya kira lebih
baik saya diam saja. Yang penting saya harus memberikan bukti. Hanya perlu
dijelaskan bahwa saya menerjemahkan dari Alquran bahasa Arab sebagai induk dan
mempergunakan terjemahan-terjemahan lain sebagai perbandingan dan memakai pula
kamus-kamus dan Konkordansi Flugel untuk mencek kembali.”
Pada akhirnya Jassin menyelesaikan karyanya dan
diterbitkan Djambatan tahun 1978 dengan judul Al-Quranul Karim Bacaan Mulia.
Mushaf dan kaligrafi dikerjakan Haji R. Ganda Mangundihardja. Buya Hamka dan
Menteri Agama Mukti Ali memberi kata pengantar.
Muncullah kontroversi. Menurut laporan Tempo, 10
Juli 1982, tak lama sesudah cetakan pertama, beberapa orang serentak
menyerangnya di media. Bermacam surat datang ke Menteri Agama atau Majelis
Ulama Indonesia, minta terjemahan tersebut dicabut dari peredaran. Terbit pula
tiga buku: Koreksi Terjemahan Al Quranul Karim Bacaan Mulia H.B. Jassin oleh
Nazwar Syamsu, Padang Panjang, Polemik tentang Al Quranul Karim Bacaan Mulia
oleh H. Oemar Bakry, dan Sorotan atas Terjemahan Quran H.B. Jassin oleh KH
Siradjuddin Abbas.
Umumnya, mereka beralasan Jassin bukanlah ulama
yang mempelajari Alquran secara mendalam sebagaimana layaknya penerjemah
Alquran. Kemampuan bahasa Arabnya juga disangsikan. Bahkan mereka keberatan
pada penggunaan sejumlah istilah dan ungkapan.
Oemar Bakry, misalnya, menuduh Jassin tak punya
cukup bekal pengetahuan agama untuk mengerjakan sebuah tugas mahapenting
seperti menerjemahkan Alquran. Dia juga menolak pemilihan judul buku Jassin,
yang dia anggap “menolahkan martabat Alquran menjadi sama dengan buku-buku lain
ciptaan manusia. Buku… bacaan bahagia, bacaan sempurna, bacaan utama, dan
lain-lain sebagainya,” sebagaimana dikutip Peter Riddell.
Sebenarnya Jassin bukanlah orang pertama yang
melakukannya. Dalam bahasa daerah, R. Hidayat Suryalaga secara bertahap
menerbitkan penjelasan Alquran dalam bahasa Sunda dalam beberapa jilid, dengan
judul Saritilawah Basa Sunda, yang dimulainya pada 1944. Menurut Peter Riddell,
pendekatannya mengingatkan pada karya Jassin, Al-Quran: Bacaan Mulia. Suryalaga
menuliskan terjemahannya berdasarkan terjemahan-terjemahan lain dalam bahasa
Indonesia dan Jawa, dan menuangkannya ke dalam dangding, syair tradisional
Sunda. Namun karyanya tak memicu penolakan seperti dialami Bacaan Mulia Jassin.
“Ini mungkin disebabkan oleh dua hal; pertama,
teks bahasa sasaran itu ditulis dalam salah satu bahasa daerah minoritas.
Kedua, dan mungkin yang paling penting, Jassin telah meninggalkan jejak yang
dapat dimanfaatkan oleh penerjemah-penerjemah lainnya,” tulis Peter Riddell
dalam “Menerjemahkan Al-qur’an ke dalam Bahasa-bahasa di Indonesia”, termuat
dalam Sadur.
Jassin sendiri sadar bahwa karyanya akan
menimbulkan polemik. Sebelum naskah itu terbit, Jassin sempat
mempresentasikannya dalam sebuah acara di Musabaqah Tilawatil Quran Nasional
tahun 1975 di Palembang. Jassin membacakan ceramahnya sepanjang 11 halaman,
menuturkan pengalaman pribadinya mengapa dia tertarik pada Alquran dan kemudian
berusaha menerjemahkannya secara puitis. Salah satunya, ujar Jassin sebagaimana
dikutip Tempo 4 Oktober 1975, semua terjemahan yang sudah dikerjakan orang
dalam bahasa Indonesia ditulis dalam bahasa prosa. Tak mengherankan karena para
penerjemah –umumnya guru agama– mementingkan kandungan kitab suci itu. Padahal
sebenarnya bahasa Alquran sangat puitis dan ayat-ayatnya dapat disusun sebagai
puisi dalam pengertian sastra.
Pembicaraan juga memasuki masalah teknis
penerjemahan. Kritik pun berdatangan. Bagi Jassin, kritik semacam itu bisa
dialamatkan ke terjemahan mana pun sebab tak ada satu terjemahan yang
disepakati semua orang. Alquran, katanya, demikian besar sehingga tak akan
habis diterjemahkan. Toh dia mau menerima sejumlah masukan. Dia juga akan
meminta pendapat orang dalam koreksi terakhir naskahnya.
Jassin mendapat dukungan dari Ustadz Mukhtar
Luthfi al-Anshari, ketua panitia Majelis Ulama DKI yang mengoreksi
terjemahannya. Katanya kepada Tempo, 10 Juli 1982: "Kebanyakan ulama
sebenarnya hanya berpegang pada sebagian saja dari kitab-kitab tafsir andalan
sebagai perbandingan." Dan di Indonesia, "biasanya yang dipegang
terutama tafsir Ibnu Katsir."
Jassin dipanggil menghadap Majelis Ulama Daerah
Istimewa Jakarta pada 25 Agustus 1976 untuk menjawab berbagai tuduhan seputar
terjemahannya.
Atas reaksi itu, Departemen Agama dan Majelis
Ulama Indonesia (MUI) bergerak. Setelah Jassin diundang dalam satu sidang para
ulama, MUI memutuskan menyerahkan masalah ini kepada MUI DKI Jakarta yang
kemudian membentuk sebuah panitia bernama Tim Perbaikan Terjemahan Al-Quranul
Karim Bacaan Mulia untuk meneliti karya itu. Panitia diketuai oleh Mukhtar
Luthfi al-Anshari. Pekerjaan itu makan waktu tiga tahun, selesai Maret 1982.
Akhirnya karya itu terbit bertepatan dengan hari
ulang tahun Jassin ke-65. Penerbitnya Yayasan 23 Januari 1942, yang didirikan
tokoh-tokoh dari Gorontalo di Jakarta seperti B.J. Habibie, J.A. Katili, Th. M.
Gobel, Ir. Ciputra, Mukhtar Peju, dan H.B. Jassin sendiri. Pada 1984, Yayasan
23 Januari 1942 juga menerbitkan karya Jassin lainnya, Juz Amma Berita Besar.
“Maka, dengan usaha Dr H.B. Jassin menulis
terjemahan Alquran, dia telah sampai pada batas yang dia sendiri tidak dapat
mundur lagi buat turut memperkuat perkembangan penyebaran Islam di tanah air
kita bersama-sama dengan teman-temannya yang lain,” ujar Hamka mengenai
terjemahan AlQuranul Karim Bacaan Mulia, seperti dikutip Pamusuk Eneste, H.B.
Jassin Paus Sastra Indonesia.
Satu masalah rampung, Jassin kembali membuat
kontroversi. Bukan hanya terjemahan Indonesia yang ingin dipuitisasikan, Jassin
pun hendak menyusun urutan tulisan Alquran secara puitis. Sejak 1991, dia
menulis ulang Alquran dalam bentuk tipografi puisi, diurutkan secara simetris.
Jika ujung ayat itu berbunyi akhir ayat "nun", misalnya, bunyi ujung-ujung
ayat berikutnya diatur pada yang berbunyi "nun" juga, begitulah
kira-kira. Penulisannya dilakukan oleh kaligrafer D. Sirodjuddin A.R. Dia sudah
mempersiapkan judulnya, Al Quran Berwajah Puisi.
Yang memotivasi Jassin: "Mengapa Alquran
yang begitu indah bahasa dan isi kandungannya tidak ditulis pula secara indah
perwajahannya."
Jassin bukanlah sastrawan pertama. Mohammad
Diponegoro (Dipo) sudah melakukannya, meski hanya juz 29 dan 30. Dipo menerbitkan
buku Pekabaran, Puitisasi Terjemahan Al Qur′an Juz ′Amma, yang diterbitkan Budaya Jaya pada 1977.
Bersama karya-karya Djamil Suherman dan Kaswanda Saleh, terjemahan puitis juz
30 Alquran gubahan Dipo dikumpulkan pengarang A. Bastari Asnin dalam Kabar dari
Langit, yang meski tak jadi diterbitkan kerap dideklamasikan dan merupakan awal
kegiatan puitisasi di belakang hari. Dipo sendiri tak menganggap dirinya
pelopor. Dia menyebut penyair Rifai Ali pada 1930-an sebagai perintisnya.
Jasssin baru mengerjakan 10 juz ketika muncul
imbauan agar tak melanjutkannya. ”Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya,”
ujar ketua Lajnah Pentashih Mushaf Al Quran, lembaga yang berwenang mengesahkan
penerbitan Alquran, seperti dikutip Tempo, 13 Februari 1993.
MUI mengajukan keberatan. Dalam suratnya antara
lain disebutkan, naskah H.B. Jassin tak sesuai dengan mushaf Al Imam, mushaf
(tulisan naskah Quran) yang menjadi standar di dunia Islam, termasuk Indonesia.
Susunan kalimat ayat yang dikerjakan Jassin juga tak mengindahkan ketentuan
qiroatnya, antara lain soal pemenggalan kalimat.
Tentu saja Jassin kecewa. Soalnya, jauh sebelum
ada larangan itu, dia sudah menghubungi orang-orang seperti Ketua Lajnah
Pentashih Mushaf Al Quran Hafizh Dasuki, Menteri Agama Munawir Sjadzali, dan
Ketua MUI Hassan Basri.
Jassin melayangkan surat kepada Hafizh Dasuki
dan Hasan Basri. Dia mempertanyakan keberatan kedua lembaga tersebut. Misalnya,
tentang apa saja mudarat dan manfaat kreasinya, tentang Alquran yang beredar
sekarang seragam dengan mushaf Al Imam yang asli, juga tentang
ketentuan-ketentuan mengenai qiraat yang paling asli.
Alquran berwajah puisi urung terbit hingga kini.
Jassin menyadari surat Asy Syu’araa (para
penyair) menyebutkan bahwa Tuhan tak suka pada penyair. Tapi, ada sambungannya,”kecuali
orang-orang yang takwa,” ujar Jassin dikutip Tempo.
Dimuat
26 Agustus 2011 di www.historia.co.id
@Redaktur SARBI: Dody Kristianto