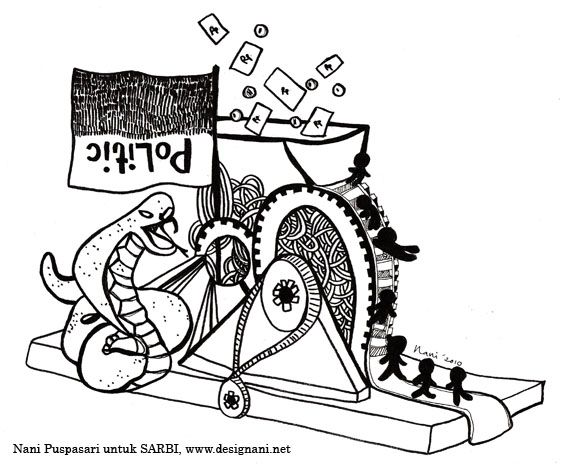
Oleh Tri Shubhi A*
Indonesia, sobongkah batu yang dicampakkan dari surga ini, sedang merangkak, belajar mengerti arti demokrasi. Pemilihan Umum merupakan kendaraannya. Bahan bakarnya partisipasi politik rakyat. Pemilihan Presiden secara langsung merupakan tonggak asasi berdirinya demokrasi di Indonesia.
Dunia memuji, Indonesia
berhasil menjalankan demokrasi. Pemilihan umum tahun 2004 berjalan relatif
lancar tanpa kerusuhan. Presiden yang terpilih secara langsung dianggap
menunjukan kecerdasan politik rakyat yang mulai meningkat. Konon rakyat tidak
lagi terikat kekuatan partai, calon presiden yang berasal dari partai medioker
pun ternyata bisa menang.
Setelah Pemilu 2004, beberapa
daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula.
Sekali lagi, Indonesia dianggap berhasil menjalankan demokrasi di tingkat
daerah. Dunia kembali angkat topi dan tersenyum manis untuk Indonesia kita.
Hanya saja ‘sukses’ tersebut
sepertinya ilusi belaka. Paling tidak sukses itu baru tercapai di tataran formal.
Artinya masih sukses sebatas pelaksanaan Pemilu atau Pilkada saja. Sesungguhnya
demokrasi di Indonesia masih tetap seperti dulu, seperti zaman orde baru.
Demokrasi tanpa logika, politik irasional.
Harus digarisbawahi bahwa
ukuran-ukuran keberhasilan demokrasi Indonesia yang selama ini diberlakukan
merupakan ukuran formal belaka. Artinya keberhasilan itu masih diukur dengan
angka dan statistik semata. Pada kenyataannya Pemilu dan juga Pilkada tetap
saja gagal menghasilkan pemimpin yang dapat memperbaiki kondisi bangsa.
Rakyat masih saja memilih
pemimpin dengan tendensi tertentu. Fanatisme terhadap suatu hal biasa menjadi
landasan bagi rakyat dalam memilih seseorang. Uang tentu saja masih memegang
peranan penting dalam dinamika politik kita. Hal lain yang tak bisa dilupakan:
mistik!
Partisipasi rakyat? Rakyat
memang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Rakyat memang menggunakan hak
pilihnya. Akan tetapi tetap saja, mereka (sebagian besar) memilih dengan
menanggalkan logika. Datangnya rakyat ke TPS lebih tepat dikatakan sebagai
mobilisasi politik oleh kekuatan politik (partai/kekuasaan), bukan partisipasi
politik yang berlandaskan kesadaran.
Penyakit ini bukan penyakit
sistem politik atau cara memilih, tetapi ini merupakan penyakit budaya.
Penyakit ini bukan penyakit hari ini saja melainkan sudah lama dan mengendap
bertahun-tahun. Kuntowijoyo ‘menggambar’ fakta-fakta ini dengan cukup apik
dalam novelnya Mantra Pejinak Ular (Penerbit Kompas: 2000).
Bagaimana yang dinamakan
politik dan politik yang bagaimana yang ada di Indonesia digambarkan melalui
sepak terjang tokoh bernama Abu Kasan Sapari. Walau mengambil latar zaman Orde
Baru tetapi cerita yang disajikan masih tetap relefan untuk dibahas. Politik
kita yang irasional dan demokrasi kita yang tanpa logika digambarkan dalam
beberapa bagian novel ini.
Hal pertama yang sangat
berpengaruh dalam perpolitikan kita ialah kekuatan yang sering dinamakan mesin
politik. Mesin politik ini yang biasanya mempertahankan keterbelakangan rakyat
untuk kepentingan kelompoknya. Mereka memanfaatkan para kiai, pondok pesantren,
tokoh masyarakat, pejabat dan apa saja yang dapat mendatangkan suara. Mesin
politik ini pun tak segan untuk melakukan penipuan, manipulasi, dan cara-cara
curang guna meraih kemenangan dalam pemilihan. Kunto menggambarkan tingkah
mesin politik ini sebagai berikut:
Mesin Politik menghendaki agar jarak waktu antara pengumuman
dan waktu pelaksanaan pemilihan singkat saja, umpamanya tiga hari, sehingga
hanya orang-orang pilihan Mesin Politik yang akan menang, sebab merekalah yang
paling siap, paling terorganisir,
orang-orangnya pasti lulus ujian, dan mesin politik itu weruh sakdurunge winarah (tahu
sebelum kejadian) karena ada rekayasa. Menang sebelum pemilihan. (hlm 91).
Banyak kenyataan yang dapat
disebut untuk membuktikan kutipan cerita di atas. Contohnya ulah mesin politik salah
satu partai di sebuah desa, Ciamis, Jawa Barat. Desa itu sedikit terpencil dan
jauh dari hiruk pikuk kota. Kebetulan jalan di desa itu rusak berat. Beberapa
hari sebelum Pemilu 2004 mesin politik sebuah partai datang ke desa itu membawa
2 buah drum aspal. Padahal aspal yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan kurang
lebih 10 drum. Mereka mengatakan 8 drum sisanya akan diberikan setelah Pemilu
berlangsung. Syaratnya partai mereka harus 100 % di desa itu. Semua berjalan
lancar. Rakyat mendapatkan 8 drum aspal dan partai itu menang 100 %.
Begitu lah politik kita.
Begitu lah ‘partisipasi’ rakyat kita. Nah jumlah angka pemilih yang cukup
tinggi tentu saja tidak dapat menjadi ukuran tingginya partisipasi dan
kesadaran politik rakyat kita. Oleh karena itu kesimpulan demokrasi berjalan
dengan baik di Indonesia, harus ditinjau ulang.
Kekuatan kedua setelah mesin
politik ialah uang. Kasus dana nonbudgeter Depertemen Kelautan dan Perikanan
(DKP) yang baru-baru ini muncul (untuk kemudian tenggelam lagi ditelan waktu)
merupakan bukti nyata bagaimana uang memainkan peran yang penting dalam
dinamika politik kita.
Sogokan dalam Pemilu atau
Pilkada merupakan rahasia umum yang telah sekian lama dianggap lumrah. Partai
atau calon yang waras ialah mereka yang menggunakan uang untuk mendapatkan
suara. Mereka yang tidak waras ialah yang ‘mengemis’ kesadaran politik rakyat
dalam pemilihan. Terbalik dan mengkhianati logika tampaknya, tetapi itulah
kenyataan politik kita hari ini.
Hal seperti itu tak berbeda
jauh dengan apa yang dikisahkan Kunto dalam novelnya. Walau berada dalam
dimensi imajinasi (yang tentu saja memiliki banyak perbedaan dengan dunia
nyata) tetapi Mantra Pejinak Ular seolah bertutur tentang kenyataan menyebalkan itu.
Perhatikan kutipan berikut ini:
…Soalnya ada kabar bahwa para botoh dari kota telah menjadikan pilihan lurah sebagai arena
perjudian. Mereka menyuplai uang untuk kampanye, dan membagi uang pada
tokoh-tokoh kunci… (halaman 96)
Rakyat kita masih banyak yang
miskin. Konsekuensi dari kemiskinan adalah keterbelakangan dan kebodohan.
Rakyat yang miskin dan bodoh ini tentu saja bersedia disogok barang Rp 50.000,-
untuk memilih seorang calon atau sebuah partai dalam pemilihan. Sekali lagi,
politik kita ialah politik tanpa rasional, demokrasi ini ialah demokrasi tanpa
logika.
Kekuatan ketiga yang
mempengaruhi dinamika politik kita ialah takhayul, mistik, atau khurafat.
Ini bukan bualan. Banyak pejabat dan calon pejabat yang bersedia datang ke kuburan
atau melakukan hal-hal mistis sejenis. Memang aneh, tetapi begitulah
kenyataannya.
Hal-hal aneh dan tidak bisa
dinalar ini justru menjadi hal yang sangat tidak aneh dalam dinamika
perpolitikan kita. Laku atau ritual
tertentu sering kali dilakukan oleh seorang calon guna meraih kemenangan
dalam pemilihan. Sebagian masyarakat kita memang masih mengandalkan mistik
dalam berpikir. Pola mikir mistik ini masih digunakan dalam sistem politik yang
(konon katanya) modern dan berlandaskan logika. Tak heran jika terjadi banyak
kontradiktif dalam politik nasional kita.
Pensakralan seorang tokohan
(baik yang masih hidup atau pun sudah meninggal), isu-isu mistik yang tak
pernah dibuktikan, dan ‘kicauan’ dukun senantiasa menghiasai dunia politik
kita. Sekali lagi, hal ini justru menjadi sebuah keanehan yang sangat lumrah.
Justru aneh kalau dalam sebuah pemilihan tak ada bau mistik. Dalam novel Kunto,
laku politik yang irasional ini digambarkan sebagai berikut:
Pada hari-H, pagi sekali sebelum matahari terbit dan sebelum
orang-orang datang, sesuai dengan anjuran dukun seorang calon lurah berangkat
menuju sendang. Ia lalu mencopot pakaian dan menceburkan diri di sendang.
Biasanya orang mandi dengan cara menciduk air sendang. Sebenarnya dingin juga
mandi dengan cara itu. Tapi dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ia yakin
betul akan memenangkan suara, karena dukun sudah menjamin…..
Dukun telah memilih gambar yang tepat, yaitu “obor”. Dia
juga telah memenuhi saran dukun untuk nyekar di makam cikal bakal desa.
(halaman 98).
Mungkin irasionalitas semacam
ini sudah jarang ditemukan di perkotaan. Akan tetapi diam-diam banyak juga
anggota DPR, DPRD, bahkan menteri yang masih percaya pada mistik. Kita tentu
belum lupa kasus penggalian situs purbakala di daerah Bogor yang dilakukan oleh
seorang menteri beberapa tahun lalu. Entah kenapa hal semacam ini begitu banyak
terjadi di Indonesia. Pendidikan formal dan teknologi ternyata tak mampu
mengikis semua itu.
Kekuatan keempat yang masih
mempengaruhi politik kita iaitu kesenian. Dangdutan atau wayangan tentu masih
sering ‘dipesan’ oleh kekuatan politik tertentu. Tentu saja saat ini yang pertama
lebih sering ‘dipesan’ dari pada yang kedua. ‘Partisipasi’ kesenian dalam
kancah perpolitikan kita digambarkan oleh Kunto dalam kutipan beriku ini:
Seorang calon lurah mengadakan wayangan
semalam suntuk, dalangnya Abu Kasan Sapari. Pertunjukan wayang kulit dimulai.
Tetapi, kursi-kursi disediakan masih
kosong, tenda yang dipasang seolah-olah tak berguna. Kursi-kursi depan hanya
diisi tamu undangan dan kader. Kursi belakang yang disediakan bagi penonton
umum nyaris kosong, ketika calon lurah berpidato. Juga ketika dia menyerahkan
wayang pada Abu –upacara penyerahan wayang yang jelas-jelas meniru para
pembesar yang diketahui melalui TV. Orang-orang ngumpet di rumah, barangkali sungkan kalau-kalau ketahuan
kaki-tangan Mesin Politik. Menonton wayang berarti mengkhianati janji, sebab
mereka sudah terima uang. Mereka hanya mendengarkan pidato calon lurah dari
dalam rumah-rumah, karena pengeras suara yang keras dapat mencapai telinga
mereka.
Namun, menjelang tengah malam, orang satu
per satu keluar rumah, mula-mula dengan bungkus sarong. Bunyi gamelan sungguh
tak terlawan. Setelah mereka yakin isu tentang adanya kaki tangan Mesin Politik
ternyata hanya satu cara memenangkan pemilihan, mereka membuka sarong dan makin
mendekat. Penonton makin lama makin banyak, akhirnya mbludag sampai jalanan. Bagi mereka yang memilih wayang, amanatnya
jelas: Pilihlah Kipas, meskipun wayangnya sama sekali tak menyinggung. (halaman
95-96)
Posisi kesenian dalam politik
memang rumit. Suatu pertunjukan kesenian tentu dapat menarik orang untuk
datang. Ketika banyak orang sudah berkumpul, kampanye tentu mudah dilakukan.
Salah satu prinsip pemilihan menyatakan bahwa yang banyak dipilihlah yang
menang. Tak heran jika kesenian, yang dapat menarik banyak orang, seringkali
aktif ‘berpartisipasi dalam kancah politik.
Sebagian orang berpendapat
bahwa kesenian harus dijauhkan dari politik sisanya justru menggunakan kesenian
untuk politik. Kunto menggambarkan kerumitan itu (mungkin juga menyatakan
pendapatnya) sebagai berikut:
Sejak saat itulah Abu Kasan Sapari selalu bertanya-tanya
bagaimana mendudukan kesenian, supaya kesenian terbebas dari politik, atau
sebaliknya politik dari kesenian, pendek kata keduanya terpisah: kesenian itu
otonom. Kesenian adalah keindahan, sedangkan politik adalah kekuasaan. Biarlah
orang lain mengotori politik, asal bukan kesenian. Mesin Politik mengotori hati
nurani dengan jabatan, botoh dengan
uang, dukun dengan klenik, dan
ada kemungkinan kesenian mengotori hati nurani justru dengan keindahan.
Mengotori dengan keindahan? Keindahan harus membuat orang bijaksana,
mempertajam hati nurani, bukan membuat hati nurani tumpul. (halaman 99-100).
Kesenian memang merupakan
keindahan. Keindahan selayaknya membuat orang menjadi bijaksana. Kesenian yang
masuk ke dalam arus politik praktis yang tidak sehat bisa jadi telah kehilangan
keindahannya.
Dinamika politik kita hari
ini belum lah sehat. Demokrasi yang diagung-agungkan telah nyata tidak dapat
menghasilkan pemimpin yang tepat bagi bangsa ini. Kualitas demokrasi kita tentu
masih pada kedudukan demokrasi irasional. ‘Partisipasi’ politik rakyat masih
diwarnai dengan kecurangan, uang, klenik, dan eksploitasi budaya bahkan
agama.
Novel Mantra Pejinak Ular setidaknya
dapat menjadi peringatan bagi kita untuk menunda kesimpulan “Demokrasi telah
berjalan dengan baik di Indonesia”. Ada hal-hal lain di luar kesuksesan
pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang tidak dapat dihitung dengan angka atau pun
statistik.
Dimuat lembar sastra SARBI edisi 2, Oktober 2010














0 comments:
Post a Comment