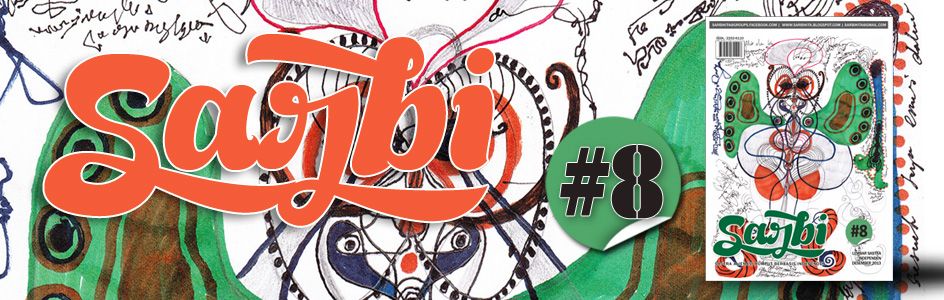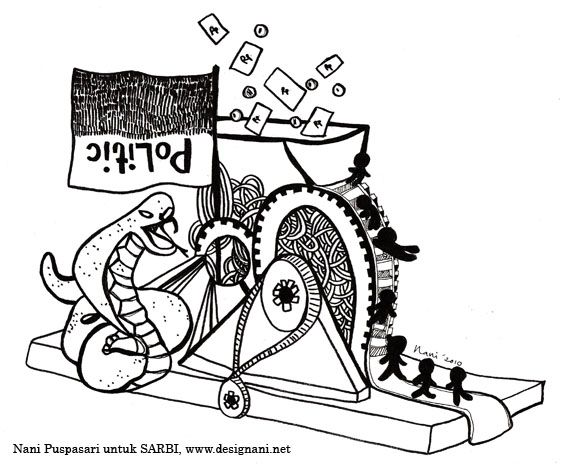R.A. Hartyanto*
Dengan mata kepala sendiri,
Fadly melihat bagaimana malaikat itu mengakhiri hidup tuannya. Orang bilang
karena stroke, tapi baginya tetap saja malaikat tadi yang mengakhiri hidup
tuannya. Tak ada sayap, tak ada lingkaran di atas kepalanya, bajunya pun juga
tak berwarna putih seperti yang biasa dilambangkan kesucian. Yang Fadli tahu,
dia datang dan pergi secepat kita menarik nafas dan menghembuskannya kembali.
Ф
Fadli hanya seorang supir
pribadi, sekolah dasar baginya ialah pendidikan tertinggi. Pernah mencuri dan
masuk bui saat keluarganya mati kelaparan akibat gempa bumi, selanjutnya hidup
di panti sampai remaja sampai ada yang mengadopsi sampai pekerjaan dia cari
sampai akhirnya diangkat jadi sopir pribadi.
Sasongko, pengusaha besi tua,
beranak lima wanita semua, istrinya tak ada, sudah mati katanya. Sekarang
Sasongko hidup sebatangkara, sudah berumur lima puluh lima, kelima anaknya
meninggalkannya pula. Anak pertama ikut suami kerja di Malaysia, anak kedua
jadi istri tentara dinas di Papua, anak ketiga pengusaha batik di Jakarta,
sedang anak keempat-kelima sampai saat ini tak ada yang tahu rimbanya.
Ф
Nafasnya tersengal, matanya
meronta tajam mengharap pembebasan. Sungguh Sasongko tidak bisa berbuat apa-apa
dalam keadaan seperti itu. Semakin parah penyakitnya, semakin mati syarafnya.
Hanya erangan rasa sakit yang bisa dirasakannya, tak ada makanan yang bisa
masuk melalui kerongkongan, semuanya harus melalui selang yang menancap di
hidung juga mulut. Sementara tubuhnya yang lemah semakin menyusut.
Pelipisnya juga semakin tirus. Sungguh tak ada kesempatan bagi Sasongko untuk
tetap hidup. Fadly yang berada di samping tempat tidurnya hanya terdiam sambil
sesekali menghela nafas panjang.
Apa yang Fadly lihat saat itu,
sama persis seperti saat kedua adiknya meninggal karena kelaparan, tatapan
matanya kosong, kerutan di dahi semakin mengendur dan dia sudah tidak mengenali
siapa-siapa bahkan sudah tak mampu mengingat apa-apa. Kepada Fadly pun Sasongko
sudah tak mengenalinya. Seperti tanda-tanda orang bakal mati, mereka mulai tak
mengenali siapa-siapa, dan tak mengingat apa-apa.
“Saya mohon Tuan bersabar,
Tuan harus kuat melawan penyakit ini”. Kata-kata yang selalu Fadly sampaikan
ketika tuannya melepas erangan. Tapi kali ini kata-kata itu terdengar lebih
berat, diiringi air mata di pipi sebelah kiri yang mendera lebih cepat dari air
mata di pipi sebelahnya lagi. Yang dirasakannya semakin merinding saat
nafas-nafas terakhir tuannya itu, dan dengan mata kepala sendiri Fadly melihat
bagaimana Malaikat itu datang mengakhiri hidup tuannya. Tak ada sayap, tak ada
lingkaran di atas kepalanya, bajunya pun juga tak berwarna putih seperti yang
biasa dilambangkan kesucian. Yang Fadly tahu, dia datang dan pergi secepat kita
menarik nafas dan menghembuskannya kembali
Ф
Tak banyak kerabat yang datang
dalam pemakaman tuan Sasongko, hanya beberapa tetangga serta rekanan usaha.
Fadly sendiri sibuk menyiapkan segala sesuatunya mulai dari peti jenazah hingga
membayar tukang gali kubur. Acara pemakaman memang tak perlu semeriah pesta
pernikah tapi jumlah para ta’ziah bagi masyarakat setempat dipercaya
menunjukkan seberapa luas pergaulan orang yang meninggal. Semakin banyak para
ta’ziah yang datang berarti kehidupan sosial bermasyarakat orang yang meninggal
sangat tinggi. Berarti pula banyak kenalan semasa hidupnya, dan baik pula
tingkah pola semasa hidupnya.
Sesuatu yang ajaib terjadi,
selang beberapa menit jenazah dimasukkan ke dalam peti mati, ada bunyi gaduh
dari dalam, seperti seseorang berusaha untuk keluar, spontan orang-orang
melarikan diri. Serasa takut bercampur heran, Fadly yang mulai gemetar terpaksa
membuka kembali peti mati itu.
Didapatinya Tuan Sasongko yang
kembali bernyawa, matanya yang keheranan bergerilya ke setiap sudut ruangan dan
semakin membuat ricuh acara pemakaman yang sepertinya tidak jadi terlaksana
itu. Rasa takut dalam diri Fadly telah dikalahkan oleh rasa tidak percayanya
sendiri. Kembali dia mendekati peti setelah sebelumnya mendadak memalingkan
diri.
“Tuan tidak apa-apa ?” Ucapnya
dengan nada bergetar. Mayat hidup itu hanya mengangguk seraya berusaha berdiri.
Sementara Fadly masih meneruskan rasa tidak percayanya. Bagaimana Tuan Sasongko
bisa berdiri jika mengingat penyakit yang diderita sebelumnya. Sepertinya tidak
mungkin. Fadly harus menyimpan kembali rasa heran setelah kemudian Tuan
Sasongko berkata, “Bawa aku ke kamar!”
Ф
Pikiran Fadly tak surut
mencari-cari jawaban, apa yang telah terjadi pada tuannya ? meski kini tuannya
bisa berjalan dan bicara, tapi saat ditanya perihal kematiannya maka jawabnya
hanya geleng kepala, sedang jika malam telah larut maka terdengar suara-suara
dari kamarnya seperti orang gila berbicara dengan Tuhannya.
Sementara itu tak ada yang
tahu pengalaman singkat Sasongko di alam yang bernama baka, bahwa mungkin telah
terjadi kekeliruan tentang kematiannya dan dia akan dijemput kembali setelah
diberitahu bakal hari kematiannya.
Hingga suatu sore masih dari
dalam kamarnya, Sasongko meminta Fadly untuk membuat sebuah ruang kosong
berdinding tebal dari bahan besi pilihan, tak ada celah tak ada lubang.
Ф
Hari itu sampai juga, hari
yang diketahui Sasongko sebagai bakal hari kematiannya, dijauhi semua hal yang
kiranya dapat membahayakan dan merenggut nyawanya. Kali ini Sasongko
benar-benar siap lari dari kematiannya, dia tidak ingin mati lagi hari ini, dia
tidak ingin menemui malaikat yang akan menjemputnya hari ini, dia ingin lari,
dia ingin sendiri. Dan masuklah Sasongko ke ruang besi itu, sendiri tanpa ada
yang menemani. Pikirnya malaikat takkan mampu menembus dinding besi ini.
Di luar, Fadly hanya mengamati
kegilaan tuannya itu, mungkinkah dia bisa lari dari mati seperti beberapa waktu
yang lalu ? Sepertinya tidak. Dengan mata kepala sendiri, Fadly melihat
bagaimana malaikat itu mengakhiri hidup tuannya. Orang bilang karena kehabisan
oksigen, tapi baginya tetap saja malaikat tadi yang mengakhiri hidup tuannya.
Tak ada sayap, tak ada lingkaran di atas kepalanya, bajunya pun juga tak
berwarna putih seperti yang biasa dilambangkan kesucian. Yang Fadly tahu, dia
datang dan pergi secepat kita menarik nafas dan menghembuskannya kembali.
Fadly hanya bergumam dalam hati bahwa tak ada yang perlu
dikhawatirkan dengan kematian. Bagaimana cara kita akan mati bergantung pada
bagaimana sikap kita melewati kematian sendiri, tak perlu lari dari kematian
karena tak ada tempat untuk bersembunyi dari malaikat pengantar mati, sekalipun
itu ruang tertutup tanpa lubang, malaikat tetap datang menyampaikan salam
Tuhan. Maka ikhlaskan…!
Kalibutuh, 27 Oktober
Untuk abah Chambali yang meninggal dunia
karena stroke
Setelah delapan tahun berjuang untuk hidup
*) RA Hartyanto, cerpenis muda, saat ini tinggal di
Bangkalan
Dimuat lembar sastra SARBI edisi 2, Oktober 2010