Ilustrasi oleh Andi Surya Nusa untuk SARBI
Oleh Umar Fauzi Ballah*
Oleh Umar Fauzi Ballah*
Membincang
sosok Chairil Anwar dan puisinya berjudul Do’a, mengingatkan saya pada awal
kecintaan saya pada puisi dan dunia sastra secara umum. Hal itu terjadi ketika
saya duduk di kelas satu MAN Sampang. Guru Bahasa dan Sastra Indonesia
memperkenalkan saya dan teman sekelas pada apresiasi puisi. Yang dijadikan
bahan ajar adalah puisi-puisi Chairil Anwar; Do’a, Cintaku Jauh di Pulau, dan
Penerimaan. Ibu guru membahas secara mendalam dalam dua kali pertemuan. Sebuah
bahasan yang juga mencakup ihwal kepenyairan Chairil hingga kematian
menjemputnya.
Entah
bagaimana kejadiannya, selama pelajaran itu saya seperti mengalami sebuah
ekstase kematian atas diri Chairil dalam Do’anya. Selain liriknya yang dalam
dan sublim, ada semacam aura yang masuk dalam diri saya untuk berkenalan lebih
lanjut dengan “binatang jalang” itu. Apalagi bila saya hubungkan dengan
kematiannya di usia yang masih begitu muda. Do’a dalam benakku bukan hanya
perihal tafsir maujud sang penyair dengan Tuhannya, melainkan juga perihal
kematian yang akhirnya menjemputnya: “Tuhanku/
di pintuMu aku mengetuk/ aku tidak bisa berpaling.”
Chairil
Anwar meninggal pada usia 26 tahun 9 bulan, yakni pada pada tanggal 28 April
1949. Usia yang relatif muda di tengah usia kepenyairannya. Sajaknya pada waktu
itu memang belum berterima oleh masyarakat, sampai ia wafat. Namun seperti yang
dikatakan oleh teman seangkatannya, Asrul Sani, dalam kata pembuka antologi
puisi dan prosa Chairil Anwar; Derai-Derai Cemara (terbitan Horison): “…aku
sampai pada suatu kesimpulan, bahwa Tuhan sudah memanggil Chairil pada saat
yang tepat. Ia meninggal di penghujung kepenyairannya. Ia merasa daya kepenyairannya
menyurut. Sajaknya yang terakhir yang ia anggap berhasil dan yang sering ia
bacakan sambil berjalan adalah Derai-Derai Cemara. Ia berkata: Hidup hanya menunda kekalahn/ Tambah
terasing dari cinta sekolah rendah/ Dan tahu, ada yang tetap tidak diucapkan/
Sebelum pada akhirnya kita menyerah.
Dalam
puisi Do’a, kematian menemukan perwujudannya yang nyata. Bagi saya, Do’a bukan
hanya soal tafsir kondisi sublim orang dalam berdoa, melainkan juga
penggambaran bagaimana kematian menjemput.
Pada
bait pertama dia menyatakan bahwa dalam (ke)termangu(an) (Chairil mengindap
penyakit paru-paru yang menggerogoti tubuhnya) ia masih bisa menyebut nama
Tuhannya: Tuhanku/ Dalam termangu/ Aku
masih menyebut namaMu. Kemudian dipertegas dengan pada bait kedua dan ketiga:
Biar susah sungguh/ Mengingat Kau penuh
seluruh// CayaMu panas suci/ Tinggal kerdip lilin di kelam sunyi, yang
menggambarkan suasana hati aku lirik merasa getaran keilahian yang benar-benar
telah mendekat kepadanya.
Pada
bait keempat sampai ketujuh Chairil hendak menggambarkan suasana yang disebut
dengan saat-saat sakaratul maut. Larik Tuhanku
pada bait keempat dan keenam yang hanya terdiri atas satu baris itu saja,
menggambarkan kondisi itu. Sebuah kondisi terputus-putusnya nafas. Dia pun
menggambarkan betapa raga yang ia miliki kini hanya benda yang sudah tak
bernyawa: aku hilang bentuk/ remuk,”
karena ruh yang tinggal di dalam raganya telah pindah ke alam lain: aku mengembara di negeri asing. Akhirnya
dia menghadap ke hadirat Ilahi Robbi. Di sini diksi Tuhan tidak lagi berdiri
sendiri, seperti pada bait keempat dan keenam, tetapi menjadi pembuka bait
terakhir, sebagaimana bait pertama. Inilah kondisi penyatuan dan kedekatan aku
lirik dengan Tuhannya, dalam panorama kematian: Tuhanku/ Di pintuMu aku mengetuk/ Aku tak bisa berpaling.
Memang,
puisi itu dibuat pada awal kepenyairannya tahun 1943. Akan tetapi tafsir kematian
dalam puisi itu akan mengena jika ditarik secara umum bahwa tema puisi Chairil
begitu dominan dengan kematian. Mungkin ini sebuah firasat yang ingin
disampaikan oleh Chairil dalam bentuk puisi. Hal ini diperkuat juga oleh
apresiasi putrinya, Evawani Alissa Ch. Anwar, sebagaimana terkutip dalam
kumpulan puisi Derai-Derai Cemara: “kalau saya ditanya mana puisi Chairil yang
paling berkesan paling dalam bagi saya, maka yang pertama harus disebut adalah
Cintaku Jauh di Pulau; Perahu melancar,
bulan memancar/ Di leher kukalungkan ole-ole buat si pacar/ Angin membantu,
laut terang, tapi terasa/ aku tidak ‘kan sampai padanya… puisi kedua adalah
Selamat Tinggal; Ini muka penuh luka/
Siapa punya?/ Kudengar seru menderu/ dalam hatiku?/ apa hanya angin lalu?
Saya merasa seakan-akan kata selamat tinggal itu semacam isyarat yang ditujukan
Chairil kepada mama dan saya..”
Evawani
yang mengetahui bahwa Chairil adalah ayahnya pada kelas 3 Sekolah Rakyat itu,
juga mengisahkan tentang cita-cita Chairil mengenai “masa depannya”: “pada
suatu ketika, Chairil berkata kepada mama, mengenai cita-citanya; ‘gajah, kalau
umurku panjang, aku akan jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,’ katanya.
(Panggilan sayang mama adalah gajah, karena badannya memang gemuk). ‘Ah, kalau
umurmu panjang kamu bakal masuk penjara’ gurau mama. Kemudian Chairil
menyambung lagi. ‘Tapi kalau umurku ditakdirkan pendek, anak-anak sekolah akan
berziarah ke kuburku menabur bunga’ demikian katanya.”
Secara
bervariasi banyak ditemukan tema kematian maupun kegelisahan dalam sajak-sajak
Chairil. Inilah sastra kamar, yaitu penyair akan mendapatkan kekhusukan dan
kepenuhan maknanya tatkala ia sadar bahwa ia tengah sepenuhnya sendiri.
Kesadaran akan hadirnya orang lain dalam situasi ini justru mengganggu
kekhusukan tersebut. Sementara kesadaran akan kesendirian menjadi sangat
penting dalam momen di mana seseorang tengah membuka perkara-perkara individualnya
dalam sebuah perjalanan ke dalam diri untuk menafakkuri keberadaannya sebagai
individu. Inilah eksistensialisme Chairil.
Perasaan
cemas akan kematian banyak disinggung dalam sajak-sajaknya: Mengapa ajal memanggil dulu/ Sebelum sempat
berpeluk dengan cintaku?! (dalam, Cintaku Jauh di Pulau, 1946). Atau sebuah
ironi: Dan aku tidak peduli/ Aku mau
hidup seribu tahun lagi (Aku, 1943). Atau sebuah firasat yang begitu
mengena akan masa depan kematiannya: di
Karet, di Karet (daerahku y.a.d) sampai juga/ deru angin. Chairil akhirnya
dikebumikan di pemakaman Karet, seperti yang ia katakan dalam puisi tahun 1949,
Yang Terempas dan Yang Putus tersebut.
***
Chairil
adalah sosok fenomenal yang menjadi perantara bagi saya pada sebuah dunia
kompleks kepenyairan. Dunia orang-orang yang senantiasa memaknai manusia, alam,
maupun eksistensi dirinya secara bijaksana dalam rangka mencari sebuah
kebenaran. Melalui Chairil, kekuasaan Tuhan berlaku bagi saya untuk (dengan
tiba-tiba) mencintai dunia kesusastraan secara luas. Berbagi suka dan duka
dengan sebuah medium seni. Memperkenalkan saya pada jiwa-jiwa yang dipenuhi
dengan ilham untuk mengatakan bahwa saya adalah bagian dari dunia dahulu,
sekarang, dan yang akan datang.
Chairil,
kemudian saya ketahui, adalah peletak dasar lahirnya kesusastraan Indonesia
modern yang secara radikal melahirkan pola ungkap berbeda dalam tradisi Melayu
yang masih eksis pada saat itu. Apa yang dikatakannya kini benar-benar
terwujud. Hari kematiannya diwarnai berbagai macam acara kesusastraan, seperti
pembacaaan puisi-puisi Chairil, sayembara penulisan esai dan sebagainya yang
menjadi kultus sendiri di bulan April. Nama Chairil juga dijadikan sebagai nama
penganugrahan sastra yang diadakan Dewan Kesenian Jakarta; Anugerah Sastra
Chairil Anwar yang kali pertama diberikan kepada Mochtar Lubis pada tahun 1992
dan kepada Sutardji Calzoum Bachri pada tahun 1998.
Umar Fauzi Ballah, penyair dan esais kelahiran
Sampang. Aktif pada berbagai kegiatan seni dan budaya.
Dimuat lembar sastra SARBI edisi #3, Februari 2011
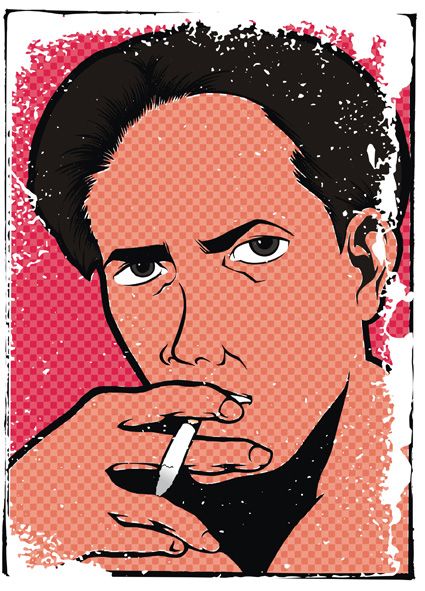














0 comments:
Post a Comment